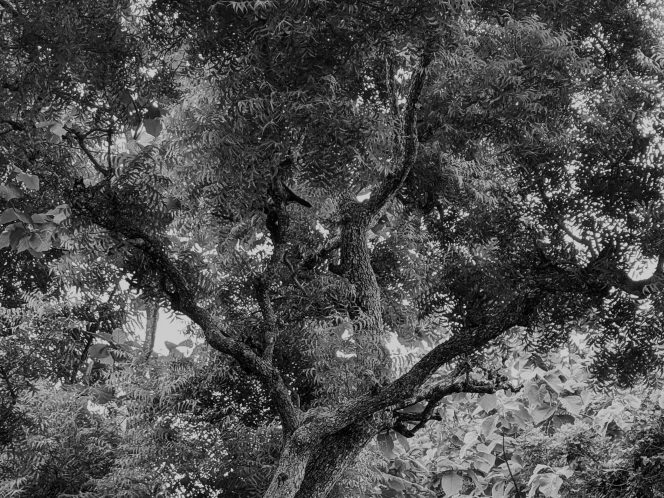“Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka,” catat kitab Kejadian 3:21. Tentu bukan kulit beruang kutub. Mungkin kulit tipis antelop atau rusa yang lebih relevan dikenakan di kebun tropis. Kuyakin Tuhan mengapresiasi kreativitas spontan mereka yang memetik daun ara untuk menutupi kemaluan. Tapi, agaknya dedaunan memang lebih cocok buat bungkus pecel ketimbang membalut tubuh manusia.
Maka, kita boleh membayangkan, dengan busana kulit, kedua manusia terkutuk melenggang di catwalk taman dan disaksikan seluruh rakyat Eden ketika hari masih sejuk. Sementara di batas timur, barisan malaikat kerub mengacungkan senjata ketika Tuhan menghalau Adam dan istrinya. Momen itu jadi tampak seperti prosesi pedang pora di pernikahan kaum halo dek.
Bisa saja kita berkata bahwa anugerah kulit hewan bukan berarti soal gaya belaka. Kehendak-Nya merefleksikan nilai-nilai holistik yang melampaui selera estetika. Sifat permanen kulit hewan seolah menunjukkan kasih Tuhan: perlindungan, keberlanjutan, dan kebutuhan esensial manusia sebagai makhluk rawan.
Namun, di luar intensitas moral yang begitu serius itu, kita boleh menduga bahwa Allah memang memiliki selera adibusana sebagaimana digambarkan novel Cain karya José Saramago saat mengisahkan detik-detik kemunculan-Nya dengan jubah penuh gelora pasca-pelanggaran tata surga. Dan karena itu, manusia macam Donatella Versace atau Oscar de la Renta semata-mata diciptakan untuk menyalurkan kegandrungan artistik Tuhan pada mode. Untungnya, peristiwa busana kulit hewan di Taman Eden tidak memancing aksi protes aktivis Greenpeace yang heran karena Sang Maha Tahu ternyata tak memiliki sensitivitas vegetarian. Jika ini terjadi, dalam tarikan napas yang sama, tempat sempurna itu bakal mengalami kericuhan ganda: dosa perdana dan demonstrasi.
Sejak awal penciptaan, Tuhan memang telah menentukan takdir semesta yang tercerai dalam ketunggalannya. Setidaknya itulah yang disinggung Karen Armstrong dalam karyanya yang masuk akal, In the Beginning: A New Interpretation of Genesis. Dua ribu lima ratus tahun sebelum Ferdinand de Saussure menyatakan iman teoretisnya tentang oposisi biner, Kitab Perjanjian Lama sudah berusaha meyakinkan kita bahwa Tuhan menakhlikkan dunia dari dua elemen berlawanan, lalu memisahkannya: terang dengan gelap, laut dengan darat, bumi dengan langit. Dan, pada akhirnya, manusia dengan surga.
Bahkan, melalui peristiwa Kejatuhan, identitas antarjenis kelamin diinsafi secara dikotomis. Ketelanjangan harfiah yang tersibak setelah insiden khuldi mendorong manusia ke arah individuasi. Transisi daun ara ke kulit binatang semacam mencerminkan bahwa fesyen lahir untuk mengaktivasi jati diri, personalitas, dan status mereka. Evolusi busana, kemudian, tak cuma menjadi simbol yang kian memperlebar polarisasi antargender, tetapi juga menumbuhkan kesadaran manusia akan posisi dirinya dalam konteks sosial dan budaya tertentu.
Akan tetapi, semirip apa pun manusia dengan Gambar Allah (Imago Dei), batas mesti ditetapkan biar ada beda, mana makhluk, mana pencipta. Itulah mengapa pasutri surga dilarang menyantap buah pengetahuan. Sebab, pengetahuan bakal membuat manusia menjadi seperti Allah sebagaimana dibisikkan Ular kepada Hawa. Setiap manusia berupaya mendekat, Tuhan seakan-akan menjerit, “Fuck off, asshole!” Dan jeritan itu meruntuhkan Menara Babel yang dibangun sebagai proyek pedekate manusia kepada Ilahi.
Di sinilah kita paham mengapa Tuhan menciptakan fesyen untuk manusia. Ketimbang hewan lainnya, secara anatomis, manusia merupakan makhluk tak atraktif. Manusia tidak punya daya pikat semarak ekor merak, surai blonde singa, dan bokong merah babun. Sebagai dampak absennya pesona zahir itu, manusia diberi fitur tak kasat, tapi cukup ampuh menyokong visi ambisius mereka ke arah nyaris ilahiah: akal budi.
Lalu, fesyen, peranti eksternal yang tak inheren dalam jasmani manusia itu, menjadi modus pertama Tuhan mengalihkan manusia dari akal budi. Motif jebakan batman ini akan efektif bila Hawa berdecak, “Oke juga, sih,” sambil berkacak pinggang saat busana kulit binatang membungkus tubuhnya. (Bukankah tragedi takkan terlalu menyedihkan jika kau meratapi nasib, sedangkan kakimu dibalut sepatu Jimmy Choo keluaran terbaru?)
Maka, kita sering mendengar stigma paradoks antara keindahan jasmani dengan kecerdasan intelektual. Kita kerap mendapati stereotipe tak adil yang dilabelkan kepada para model sebagai golongan yang memiliki kecantikan ideal, tapi berotak udang. Kita acap melihat orang yang terlalu fokus pada penampilan fisik tidak punya cukup waktu mengasah ketajaman kognitif. Kita membaca filsuf kafe Simone de Beauvoir memperingatkan gendernya supaya tak sibuk berdandan agar meraih kesetaraan eksistensial dengan manusia pria.
Itulah mengapa genealogi fesyen mestinya juga menjadi penanda transformasi spiritual. Katakanlah dalam tradisi teologis, hadiah kulit hewan bisa dilihat sebagai simbol pengorbanan yang akan mengusik sisi patos kita yang paling rentan. Kulit binatang adalah kata lain darah yang harus ditumpahkan. Kejadian tersebut memang kerap diartikan sebagai kurban pertama dalam narasi Biblikal. Dengan demikian, peristiwa ini memantulkan prinsip absolut bahwa dosa membawa konsekuensi tak murah, tetapi Tuhan menyediakan solusi dengan memberi manusia “pakaian” layak.
Karena industri, kini kita cenderung menjatuhkan fesyen ke derajat banal hanya demi pengakuan sumir. Apa yang sudah kita renungkan seyogianya dapat membersitkan rasa syukur bahwa, kendatipun alergi pada sikap eska-esde manusia, paling tidak Tuhan telah menawarkan suaka yang memungkinkan spesies kita tetap sintas hingga detik ini. Maka, ketika sudah tahu bahwa sebuah laku konsumsi menuntut harga mahal, kita mesti ingat bahwa limbah tekstil yang kita jahit telah mencemari mata air, sabun yang kita pakai telah menggusur habitat orangutan, dan jam tangan yang melingkar elegan di pergelangan tangan telah mengeksploitasi ribuan bocah Afrika kelaparan.
Royyan Julian menulis puisi dan prosa.
Editor: Ikrar Izzul Haq