Saya lahir dan dibesarkan di kultur pesantren. Namun belakangan saya sadar, pesantren dengan intim mulai saya kenal justru bukan melalui lingkungan empiris di mana saya lahir, melainkan fantasi yang saya dapati melalui semesta kisah-kisahnya. Setidaknya sejak mulai menginjak usia sekolah dasar, saya terbilang doyan membaca biografi-biografi ulama pesantren. Untuk contoh belaka, saat kelas tiga sekolah dasar, saya membaca Jejak Spiritual Kiai Jampes (LKIS, 2008) hasil ikut bapak mampir di toko kitab saat menyambangi kakak di Lirboyo.
Saya ingat, saya pun punya buku berjudul Gus Maksum: Sosok dan Kiprahnya (Lirboyo Press, 2004); sebuah buku biografi yang di kemudian hari, membuat saya sempat gandrung pencak silat. Ada juga TawaShow di Pesantren (LKIS, 1999), sejenis himpunan kisah-kisah jenaka di pesantren. Karena watak kisah-kisahnya yang jenaka itulah, ada satu judul cerita yang masih demikian menancap di kepala saya hingga hari ini, yakni kisah tentang Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras yang berbagi rokok dengan santrinya. Saya ingin ceritakan ulang untuk mengenang bacaan masa kanak-kanak itu. Begini.
Di pesantren, saling gantian mengisap sebatang rokok, merupakan tradisi yang lumrah. “Saksedotan” menjadi pernyataan yang dalam tradisi ini. Ia sejenis tinanda yang disepakati bersama apabila kita bermaksud untuk minta satu hisapan, katakanlah, pada seorang kawan yang sedang mengudut. Tradisi ini umumnya dijalankan hanya antarsantri, terlepas mereka sudah saling kenal atau tidak sama sekali. Tak jarang, satu batang rokok bisa diisap secara bergantian oleh tiga orang, bahkan lebih.
“Sak sedotan, Kang,” kata seorang santri, suatu malam, begitu ia melihat seseorang yang tak begitu jelas siapa tengah duduk santai sambil mengisap rokok. Ia sesungguhnya tak tahu bahwa yang ia sedang panggil dengan sebutan “kang”— panggilan yang lumrah untuk memanggil sesama santri—adalah kiainya sendiri. Kegelapan malam telah melamurkan wajah si empunya rokok, yang saat itu sedang duduk memandangi bangunan pesantren yang ia dirikan. Mendengar kode itu, spontan saja si empunya rokok—Kiai Wahab—pun mengulurkan rokok yang terselip di sela jari-jarinya. Bagaimanapun, Kiai Wahab tentulah juga seseorang yang pernah nyantri sehingga ia pun biasa dengan tradisi berbagi isapan semacam itu.
Tanpa sedikit pun menaruh curiga, si santri menerima rokok yang diulurkan Kiai Wahab kemudian mengisapnya dalam-dalam, begitu khusyuk dan nikmat. Bara api rokok yang ia hisap pun membuat kegelapan malam sedikit tersingkap. Bara yang menyala dari ujung rokok itu kontan menerangi wajah si empunya rokok. Barulah si santri sadar bahwa orang yang sebelumnya ia panggil enteng dengan “kang” untuk ia minta berbagi isapan itu, tak lain adalah kiainya sendiri. Entah karena malu ataukah saking gugupnya, si santri itu pun lintang pukang melarikan diri, tanpa sadar kalau ia masih membawa serta rokok Kiai Wahab di sela jarinya. Kiai Wahab pun, sialnya, mengejar santrinya itu sambil berteriak-teriak, “Hei, rokokku! Rokokku!”. Jadilah malam itu, kiai dan santri bagai memerankan adegan seorang hansip yang sedang memburu seorang maling.
Selain dari buku-buku biografi sejenis yang sering saya comot dari etalase koleksi buku dan kitab-kitab bapak, kisah-kisah yang masih bertalian dengan ihwal dunia kepesantrenan juga kerap saya simak dari cerita-cerita yang dituturkan bapak sendiri. Misalnya, kisah masyhur mengenai Syekh Barseso—seorang ulama yang dalam kisahnya, dikarakterisasikan sebagai sosok alim, ahli ibadah, tetapi berujung nahas saat ajal menjemput karena gagal menahan goda—atau, kisah tentang Khalifah Umar dengan seekor burung emprit. Di kemudian hari, barulah saya ketahui bahwa kisah-kisah, yang dalam penuturan ulangnya sering jadi kian fantatis melebihi versi asli laiknya narasi gosip itu, rupanya bersumber dari literatur kitab kuning—sumber rujukan penting di dalam tradisi keilmuan pesantren.
Namun, dari sekian buku biografi ulama yang pernah saya baca, barangkali buku berjudul Gus Maksum: Sosok dan Kiprahnya itulah yang begitu berkesan di benak dan ingatan saya kemudian. Di usia saya yang masih amat belia saat itu, saya sempat terpukau mendapati kisah Gus Maksum kecil yang (konon) mampu membuat anak sapi terkapar hanya dalam sekali tendang. “Sakti benar orang ini,” batin saya, tak percaya. Di kemudian hari, kekaguman pada sosok ulama yang kondang dalam olah bela diri dan ilmu kanuragan itu, tanpa saya sadari telah memberi saya sejenis dorongan untuk bertekad masuk ke lembaga pesantren. Bukan dalam rangka mengisi buli-buli pikiran dengan berbagai ilmu keagamaan, melainkan menjadi seorang pendekar, persis sosok yang telah khatam saya baca jejak dan kiprahnya sejak usia dini. Maka, aktivitas bela diri, selama tak kurang dari enam tahun, turut memberi warna tersendiri pada hari-hari saya selama nyantri di pesantren tempat dikebumikannya sosok kiai-pendekar itu.
Meski menjajal hasil latihan ilmu silat di ajang tarung bebas sempat menjadi kesenangan tersendiri pada masa-masa remaja, saya tak pernah benar-benar menjadi seorang pendekar. Saya sadar, sebagai pengidap asma turunan, saya jelas tidak cocok untuk menjadi manusia sejenis Jaka Tingkir. Dan kalaulah di dada yang kadang suka mengkis-mengkis ini saya torehkan tato 212 sekalipun, saya juga tak akan tiba-tiba sesakti Wira Sableng. Apa pun itu, demikianlah memang niat saya pertama-tama masuk ke pesantren. Lagipula, meski gagal mewujudkan mimpi masa kanak-kanak, paling tidak, aktivitas bersilat-ria itu telah membikin badan saya sehat, asma saya jarang kambuh, dan menjadi wahana hiburan tersendiri.
Saya katakan menjadi wahana hiburan karena di pesantren, kami, para santri, memang tidak diperkenankan untuk bersentuhan dengan gawai. Jadilah kami tidak seperti umumnya remaja pada masanya, yang bisa bebas bermain media sosial di laman Facebook dan Twitter, sambil menyimak lagu-lagu kesukaan lewat YouTube. Situasi hari-hari dengan tanpa adanya gawai yang melingkupi kehidupan kami itu, tidaklah semengerikan yang kalian bayangkan. Tidak juga semembosankan yang mungkin kalian khayalkan. Yang di kemudian hari saya kenali sebagai “sastra”-lah, yang membuat kehidupan remaja saya tidak lantas lekas berdebu—selain juga kesenangan pada pencak silat itu.
Di waktu-waktu luang usai menjalani rutinitas sekolah dan madrasah diniah, saya ingat benar, kami para santri memiliki tradisi sebagaimana berbagi isapan rokok dalam objek yang sama sekali lain, yakni “bertukar bacaan”, khususnya adalah novel. Apa pun genrenya. Tidak hanya novel-novel populer bertemakan Islam atau kepesantrenan, tetapi juga novel-novel picisan yang bahkan nama pengarangnya pun tak akan terlacak oleh radar sejarah keadiluhungan sastra Indonesia. Sebagai permisalahan, Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy, Cinta di Ujung Sajadah anggitan Asma Nadia, Sujud Hati di Ujung Shubuh karya Indah El-Hafidz, Dilan karya Pidi Baiq, bahkan novel-novel romantis-jenaka karya Raditya Dika (Cinta Brontosaurus, misalnya). Saban kali sebuah novel yang menurut tuturan mulut ke mulut disebut menarik, novel tersebut akan lekas berpindah dari tangan satu santri ke santri yang lain, melintasi tembok-tembok bilik, berpindah dari asrama yang berjauhan satu dengan lainnya. Jika memang mujur, novel itu akan kembali ke pelukan si pemilik. Jika tidak, ikhlas adalah satu-satunya pilihan mutlak. Demikianlah.
Membaca prosa-fiksi tidak hanya menjadi kegemaran, tetapi semacam usaha kami dalam mencegah kehidupan yang terisolasi dari gemerlap dunia luar supaya tidak lekas terasa usang. Kesenangan ini sesungguhnya kami jalani bagaikan menyembunyikan sebuah aib. Di pesantren salaf kebanyakan, membaca karya sastra—sebagaimana membuang waktu dengan bermain gawai—dianggap sebagai aktivitas yang jamak disebut lelahan, yakni kegiatan yang (diyakini) dapat membuat seorang santri lalai, sehingga ia terpiuh dari tujuan utamanya dalam menimba ilmu agama. Pada taraf yang lebih ekstrem, membaca karya fiksi diyakini juga akan menjadi lumantar si santri menjadi lupa kepada Tuhannya. Itulah sebabnya, selain barang elektronik (ponsel, pemutar musik, atau flashdisk yang disimpan diam-diam oleh beberapa santri), novel juga menjadi sejenis benda haram yang ketika Divisi Keamanan pesantren melakukan razia ke bilik-bilik santri. Maka, jika seorang santri ketahuan memilikinya, konsekuensinya ialah pembredelan.
Hal yang menurut saya paradoks adalah karena mading dan majalah di pesantren kami pun sesungguhnya menyediakan kolom cerita fiksi. Belum lama ini, saya coba cek, pesantren saya kini bahkan memiliki rubrik cerita pendek santri di situs daringnya. Saya, yang dulu pernah bermimpi jadi manusia sejenis Jaka Tingkir sekaligus bercita-cita jadi penulis sekelas Habiburrahman El-Shirazy, pernah juga mengirim beberapa naskah cerita pendek saya ke alamat redaksi majalah tersebut, walau ujung-ujungnya ditolak melulu. Saya pun ingat, di Pondok Induk, yang bahkan tak menyediakan lembaga pendidikan formal seperti unit yang saya tempati, juga mempunyai mading yang juga rutin menayangkan cerita-cerita pendek khas dunia kepesantrenan.
Saya ingat karena saya pembaca yang selalu siaga dan antusias menunggu rilisan edisi terbaru, semata-mata demi mengudap suguhan cerita pendek terbaru, juga komik anekdot tentang berbagai persoalan kepesantrenan yang ditayangkan di mading legendaris itu. Mading-mading, baik yang ada di unit yang saya tempati, maupun yang dipajang di tembok sisi utara masjid Pondok Induk tersebut, nyaris selalu penuh sesak oleh para pembaca setiap kali edisi terbarunya ditayangkan. Dari yang habis mengaji bandongan dengan kitab masih tersangkur di lengan, yang sengaja mampir sekalian menunggu antrean kamar mandi, hingga yang tampak sekadar kurang kerjaan sambil asyik mengunyah sebungkus makroni pedas juga turut mengerubungi mading.
Akan tetapi, sastra yang turut menyelamatkan—khususnya pada saya pribadi—dari bahaya laten kejenuhan lingkungan yang terisolir itu, tidak hanya prosa-fiksi, tetapi juga puisi—persisnya, puisi yang ditembangkan, baik dalam serangkaian kegiatan madrasah diniah maupun sekadar aktivitas pengisi waktu luang keseharian. Di pesantren, aktivitas ini lazim disebut dengan istilah “lalaran”, ada juga yang menamainya “nadzaman”, maksudnya yakni melantunkan nadzam: sebuah bentuk dari matan (teks primer kitab kuning) yang (terkadang) disusun dalam prosodi persajakan bahasa Arab (matra, rima, irama). Oleh karena itu, matan dalam konteks ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, adalah teks inti atau dasar dari suatu disiplin ilmu yang wajib untuk dihafal oleh para santri karena menjadi syarat untuk ujian kenaikan tingkat (katakanlah, dari tingkat aliah 1 menuju ke aliah 2). Tidak semua matan kemudian wajib dihafal. Hanya matan-matan tertentu, semisal Alfiyyah ibn Malik atau al-Imrithi (dua matan dalam ilmu nahu yang disusun dalam prosedur ketat puisi arud’—puisi berirama dalam bahasa Arab—di mana baris satu ke baris selanjutnya dipenggal oleh jeda baris dengan mempertahankan keselarasan persajakan) merupakan dua contoh yang wajib dihafalkan. Adapun me-nadzam-kan atau melafalkan kedua matan tersebut dengan melagukannya, hanyalah sejenis cara supaya lebih gampang dalam menghafal belaka.
Itulah perkenalan saya dengan sastra untuk kali kedua (setelah sebelumnya melalui prosa-fiksi), yang kebetulan, bertepatan dengan masa naiknya jenjang madrasah saya menuju ke kelas aliah. Di masa ini jugalah saya menginjak usia remaja yang, secara biologis, membuat saya mulai tertarik kepada lawan jenis. Betapa pun saya dan kawan-kawan paham bahwa aturan telah menerbitkan larangan untuk berkontak dengan lawan jenis, di hadapan remaja-remaja jatuh cinta aturan hanyalah kalimat kosong nirmakna. Tentulah diperlukan siasat tersendiri untuk menjalankan komunikasi dengan lawan jenis itu supaya kami tak ketahuan telik sandi keamanan, supaya tak kena takzir atau hukuman.
Di masa-masa pencarian yang menghendaki kebebasan, tetapi justru penuh pengawasan itu, surat menjadi medium yang diandalkan oleh para santri—termasuk saya—untuk berkomunikasi dengan santriwati, yang diam-diam, telah mencuri hati. Nyaris semua kawan laki-laki saya dulu, terutama yang memiliki pacar atau sekurang-kurangnya menaruh perasaan pada santri putri tertentu, memiliki semacam buku diary. Namun jika dibuka, diary itu rupa-rupanya tidak selalu berisi catatan harian, melainkan korespondensi yang ditulis tangan dalam wujud secarik surat antara si pemiliknya dan kekasih atau perempuan yang diam-diam sedang ia damba.
Ada satu kenangan yang sampai sekarang saya ingat betul dari masa-masa ini. Oleh karena tak semua kawan saya becus menuangkan perasaaannya ke dalam kata-kata, saya, yang bagi mereka dinilai andal, sering dimintai bantuan untuk menuliskan secarik surat cinta. Sebab di dunia ini tidak ada yang gratisan, walhasil, saya pun menetapkan tarif. Untuk secarik surat cinta, berikut kesediaan sepasang kuping saya menyimak curhatan-curhatan klien saya yang sial itu, saya banderol dengan segelas kopi hitam Brontoseno dan sebungkus rokok Surya 12. Jika klien saya sedang baik, tak jarang saya juga ditraktir sepiring mie Sedaap goreng racikan Kang Kantin. Harga yang cukup untuk ukuran bocah SMA. Ah, lupakan. Kita kembali menyoal tradisi melafalkan matan.
Pada dasarnya, prosodi ketat dalam susunan matan yang masih merupakan tradisi perpuisian Arab jaman lampau itu, memanglah dimaksudkan supaya matan mudah dihafalkan. Orang-orang Arab, pada masanya, menyimpan dalam ingatan mereka harta karun masa lalu, lewat puisi sebagai mediumnya. Persis para cendekiawan yang mengingat silsilah kesukuan (ansab) dan peperangan (ayyam), juga mengingat lewat medium serupa. Bukankah menghafal pantun tentu lebih mudah daripada menghafal kalimat-kalimat dalam prosa? Begitulah kira-kira gambaran sederhananya.
Tentang ini, saya teringat dan karenanya, saya ingin mengutip puisi karya K. H. Mustofa Bisri. Seorang ulama’-penyair, yang dulu juga merupakan alumnus pesantren yang pernah menjadi tempat saya nyantri itu, pernah menulis sebuah puisi berjudul “Lirboyo, Kaifa Haal?”
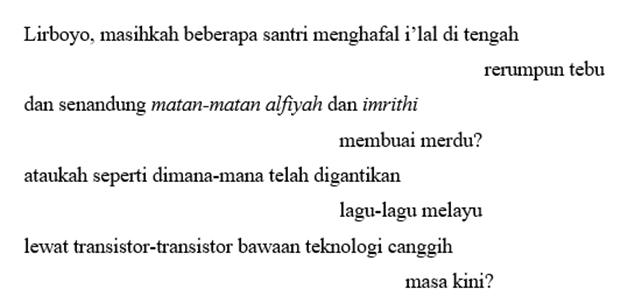
Saking berkesannya puisi ini di ingatan saya, saya pun pernah menulis puisi yang terinspirasi dari puisi “Lirboyo, Kaifa Haal?” karya Gus Mus.
Mengenang Lirboyo
Di Lirboyo,
di bawah teduh rumpun bambu yang khusyuk menadah terik
di sela silamu pada gelar sajadah itu,
tengah kau torehkan tarikh
pada lembar-lembar jalalain yang sunyi.
Malaikat bentangkan sayap
di cerlang langit lazuardi yang biru,
yang menggantung di atas pecimu.
Di kejauhan, kidung ampunan disenandungkan
mulut-mulut ikan dari lubuk laut serupa untaian zikir
yang istakamah kau lampir di gawir malam,
atau bebait nazam dan serentet washilah
yang sering kau rapal di khidmat ziarah.
Di Lirboyo,
ketika lembayung teja telah purna
di balik punggung Klotok yang ngungun,
bergegaslah kau ayun langkahmu menuju nun.
Kelebat sarung yang bersarang di lesat kakimu itu adalah tanda;
betapa “nawaitu ta’alluma”
semasih tegak berkibar di kobar dadamu.
Lantas jurumiyah,
Lantas amtsilah,
Lantas imrithy,
Lantas alfiyah,
Masihkah terus menggema
getarkan batang-batang tebu,
yang serupa teguh kasdu di sunyi dadamu?
(2019)
Boleh dibilang, inilah puisi yang kemudian membuat saya akhirnya memutuskan untuk terus menulis puisi, setelah sebelumnya saya sempat bertaruh bahwa jika puisi “Mengenang Lirboyo” ini tidak menang dalam suatu kompetisi yang sebetulnya “kecil” belaka dulu itu, saya bersumpah untuk berhenti menulis puisi. Selama-lamanya. Baiklah. Kita kembali menyoal puisi Gus Mus.
Puisi yang, seingat saya, pernah dibacakan Gus Mus di acara Satu Abad Lirboyo itu, selain menunjukkan bahwa melafalkan baris-baris matan berbentuk nadzam secara bernada telah menjadi pengalaman yang menubuh dalam kehidupan santri di pesantren. Namun, bukan itu persisnya yang ingin saya cetak tebal. Pesantren, sebagai tempat yang mempertemukan saya dengan sastra, wabilkhusus puisi (dan siapa sangka di kemudian hari, saya akhirnya banyak menulis puisi) rupa-rupanya menyuguhkan “bunyi” alih-alih “arti” sebagai titik perkenalan saya mula-mulanya.
“Lirboyo, masihkah beberapa santri menghafal I’lal di tengah/ rerumpun tebu/ dan senandung matan-matan alfiyah dan imrithi/ membuai merdu?” tulis Gus Mus dalam baitnya, dan saya pun lantas terbayang bagaimana dulu gema para santri yang me-nadzam-kan matan-matan dengan nada, seakan serupa orkestra. Bunyi itu merambat dari dinding-dinding kelas madrasah, menimbulkan sejenis gentar di satu sisi, juga takjub di sisi yang lain.
Bunyi, dalam tradisi melafalkan baris-baris nadzam dengan bernada itu, mula-mula menghasilkan hubungan yang bersifat auditif ketimbang kognitif dengan si pelafalnya. Yang auditif hadir mendahului yang kognitif. Maka si pelafal atau si pendengar “senandung matan-matan alfiyah dan imrithi” terbuai bukan oleh makna yang terkandung, melainkan kemerduan yang mengemuka.
Demikian halnya saya, sewaktu dulu me-nadzam-kan atau melafalkan baris-baris puitis kitab matan seperti Alfiyah atau Imrithi dengan nada tidak begitu menjadikan “arti” sebagai aspek penting untuk diperhatikan. Arti, berada di satu anak tangga di bawah bunyi, di bawah musikalitas. Selepas susunan kata berima itu, barangkali jugalah imaji baru dapat kita tangkap manakala kita mengerti artinya.
Jauh di kemudian hari, saya pun juga baru menyadari, bahwa betapa banyak judul-judul kitab kuning yang mengandung musikalitas dalam susunan kata berima sehingga membuatnya terasa seperti baris nan puitis. Sebagai satu contoh belaka, sebutlah kitab Nashaihul ‘Ibad fi Bayani Alfadh Munabbihat ‘alal Isti’dad Liyawmil Ma’ad—sebuah kitab syarah karangan Syekh Nawawi al-Bantani, dari matan berjudul Munabbihat ‘alal Isti’dad Liyawmil Ma’ad yang dianggit oleh Ibnu Hajar al-Asqalani—atau Bughyah al-Mustarsyidin fi Takhlish fatawa Ba’dh al-Aimmah al-Muta’akhkhirin—kitab fikih yang menghimpun fatwa para ulama madzab Syafi’i mutakhir—anggitan Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’alawi al-Hadrami. Ketika saya mencermati ulang bagaimana saya menulis puisi, baik pada buku pertama maupun kedua yang baru saja lahir, saya sadar bahwa bagaimana bahasa puisi yang saya alami sebagai pengalaman kebahasaan, mula-mulanya, dibentuk oleh atmosfer yang lahir dari tradisi di pesantren yang melingkupi kehidupan saya, nyaris empat belas tahun lamanya itu.
Yohan Fikri adalah penyair cum kritikus sastra. Buku puisi terbarunya, Anjing-Anjing Lepas Amarah (2025) menerima Anugerah Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur.
Editor: Ikrar Izzul Haq













