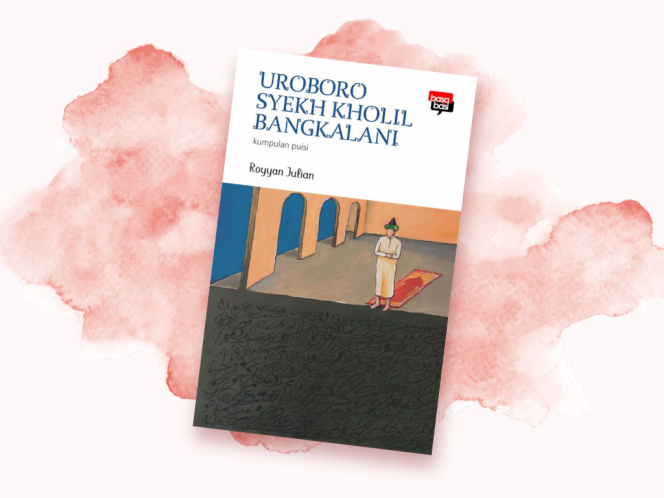Tulisan ini akan saya buka dengan menukil pembukaan The Death of the Author karya Roland Barthes:
“Dalam kisah Sarrasinenya, Balzac menggambarkan seorang kastrato yang menyaru sebagai perempuan dengan kalimat berikut: ‘Itulah Perempuan, dengan ketakutan mendadak, dengan keinginan-keinginan irasional…’ Siapakah yang sebenarnya berbicara dalam kalimat ini?”
Dalam buku The Human Comedy (La Comedie humaine)—karya Balzac yang mengalusi pada Divine Comedy karya Dante Alighieri—Sarrasine muncul sebagai seorang pematung Prancis yang jatuh cinta kepada La Zambinella, seorang penyanyi opera Italia. Sarrasine sang pematung itu terpesona betul pada keindahan dan kemolekan Zambinella. Hingga kemudian tiba identitas Zambinella terbongkar, bahwa ia sebenarnya seorang kastrato: seorang pria yang dikebiri sebelum masa pubertas agar suara sopran atau altonya tetap terjaga. Sarrasine mengetahui fakta menyakitkan itu, lalu ia mengalami krisis gairah, identitas dan kehancuran. Sarrasine dalam La Comedie humaine itu merupakan kisah yang memetamorfosa rasa kagum jadi tragedi. Karya Balzac ini jadi magnum opus sebab menghadirkan—di abad ke-19—sebuah ambiguitas gender dan identitas, di mana Zambinella beridentitas laki-laki sekaligus perempuan; ia berada dalam situasi in-between liminalitas gender.
Oleh karena ruang liminal yang tak memiliki batas tegas, Barthes memperkarakan siapakah yang berbicara dalam sepenggal kalimat dalam La Comedie humaine itu? Balzac? Sang narator? Atau bahasa itu sendiri?
Voila! Jika kita membaca Oroboro Syekh Kholil Bangkalani karya Royyan Julian dengan saksama, pertanyaan serupa juga hadir. Siapakah yang berbicara dalam buku puisi ini? Royyan? Narator dari masa lalu? atau bahasa itu sendiri?
***
Mari kita mulai dari akhir.
Di bagian blurb buku terbaca: “Oroboro Syekh Kholil Bangkalan bukan hanya penulisan ulang, melainkan remitikalisasi melalui tafsir melingkar Paul Ricoeur atas kultur, sejarah, serta legenda Madura.”
Dari sepenggal kalimat di blurb ini, kita bisa memberikan dua saripati betapa antara Royyan, teks masa lalu, dan bahasa saling salin menyalin.1
Pertama, karena puisi ini sebentuk tafsir melingkar a la Ricoeur, membentuk penafsiran long detour yang najis pada jalan pintas, maka semesta masa lalu Madura itu, di tangan Royyan, bukanlah sebuah masa lalu yang sudah bulat. Terdapat asumsi diam-diam Royyan bahwa Madura merupakan sebuah entitas yang-menjadi dan perlu ditafsir ulang sedalam-dalamnya. Oleh karenanya, alusi dari buku ini jelas belaka, yakni sembarang semesta yang berkait dengan kultur, sejarah, dan legenda Madura. Oroboro Syekh Kholil Bangkalani ini, sebagai puisi, benar-benar berperkara dengan sejarah.
Kedua, sejarah dan masa lalu Madura. Madura, sebagai sejarah dan latar hidup sang penyair, mengintervensi kuat proses kreatif buku ini. Artinya, tidaklah mungkin melepaskan puisi ini dari konteks dan latar sang penyair; ketidakmungkinan menafsir semata-mata dari sudut pandang internal karya. Sejarah, dengan segenap kontur sosiologisnya, adalah modus operandi sekaligus modus procedendi dalam buku ini. Hal ini menyebabkan buku ini tak bisa lolos dari kerja-kerja historisisme.
Dua skema di atas pada akhirnya membentuk dialektika. Royyan dengan sejarah saling berdialog, saling menambah dan membantah satu sama lain. Royyan menafsiri sejarah; dan sejarah mengilhami dan mengondisikan Royyan. Satu sama lain saling mengontaminasi, dan buku puisi ini, pada akhirnya, tidak ada lagi batas tegas suara siapa sebenarnya yang berbicara. Sejarah yang telah ditafsir, toh, sudah menjadi suara Royyan; tapi pada saat yang sama, roh sejarah itu belum jua lesap total dan masih memiliki suara dan peran genting.
Kita bisa meringkas demikian: kerja penafsiran long detour yang dilakukan Royyan menyebab si aku-lirik jadi goyah. Persis di situ, kita tidak lagi bisa mengidentifikasi apakah suara Royyan atau sejarah yang berbicara. Barangkali serentak, umpama satu raga yang terdiri dari dua roh. Lantas, siapakah aku-lirik dalam sehimpun sajak ini? Royyan? Atau narator dari masa lalu? Kedua-duanya, serentak. Dalam skema “sajak-historis” yang bersumber melalui aktivitas penafsiran2, suara yang terdengar adalah suara sang penyair sekaligus suara sejarah.
Dan, di tengah-tengah antara Royyan dan sejarah itu ada bahasa puisi. Lelaku tafsir itu tak dijadikan rancang-bangun prosa yang serba komunikatif dan memiliki alur yang bulat; melainkan jadi sajak yang, kita tahu, menjauh sejauh-jauhnya dari komunikasi. Perihal ini, kita setidaknya bisa mengutip T.S. Eliot dalam “The Metaphysics of Poetry”:
“Peradaban kita mencakup keragaman dan kompleksitas yang besar, dan keragaman serta kompleksitas ini, yang berinteraksi dengan kepekaan yang halus, harus menghasilkan hasil yang beragam dan kompleks. Seorang penyair harus menjadi semakin komprehensif, semakin samar, dan semakin tidak langsung, agar dapat memaksa, bahkan mendesak jika perlu, bahasa untuk menyesuaikan diri dengan maknanya.”3
Royyan seolah menerapkan apa yang dikata Eliot ini. Sejarah-Madura sebagai peradaban yang begitu beragam itu, disuling dan menjadi sebentuk sajak yang sangat komprehensif, samar, dan semakin “tidak langsung”. Artinya, sejarah-Madura yang ditransformasi jadi sajak itu menjadikan Madura yang-lain dan samar-samar. Di tangan Royyan, sajak menjadi alat untuk melenturkan sejarah Madura yang—semoga saya tak keliru—terlanjur beku.
Sejarah yang menjadi sajak juga tak bisa lolos dari pelbagai resiko. Kita tahu, puisi tak hendak menerangkan fakta, apalagi berhasrat mengungkai sejarah demi menggenggam kebenaran tertentu. Sembarang sajak—tentu saja sajak yang ideal—memalingkan dirinya sepenuh-penuhnya pada mimetisme. Sejarah yang merangsek masuk ke dalam jagat sajak akan kehilangan sauh kebenaran dan terputus pada fakta-fakta masa lampau. Jika pun ada fakta-fakta sejarah yang hendak disampaikan dalam sebuah sajak, ia mustilah bersembunyi dalam selaput-selaput metafora, personifikasi, majas, imaji, densitas…
Dengan demikian, sejarah yang tampak dalam sajak adalah sejarah yang abu-abu, begitu samar, dan hanya jejak-tilas (jejak atas jejak). Sejarah pada akhirnya jadi medan lentur yang maknanya bisa ditarik ke sembarang mata angin. Di hadapan sajak yang demikian, pembaca sekurang-kurangnya dihadapkan pada dua pilihan: menyigi semata-mata permainan perlambang dengan segenap bunyi, di satu sisi; atau mengaitkannya—jika memungkinkan—dengan dokumen sejarah, di sisi lain.
Singkatnya, saya hendak mengatakan bahwa puisi historis bisa dibaca dengan atau tanpa dokumen sejarah. Jika dibaca dengan dokumen sejarah (baca: dengan hipogram), puisi akan jadi jembatan dan pintu masuk ke dalam labirin masa lampau. Dan, jika tanpa dokumen sejarah (baca: tanpa daya dukung hipogram), puisi historis jadi siasat persajakan yang otonom belaka; di mana tafsir atas makna akan terbang bebas dan sering mengkhianati arti.
Jika kita membaca “Todesfuge” karya Paul Celan, misalnya, sajaknya itu bisa dibaca semata-mata dalam kacamata bentuk: “Susumu susu hitam fajar, kami minum pada sore hari.” Sepenggal larik pembuka ini, tanpa mengaitkannya pada Holocaust sekalipun, puisi ini tetap bisa dinikmati sebagai permainan bahasa. Dalam pembacaan yang demikian, kita tak membutuhkan daya dukung hipogram.
Namun, jika kita membaca dengan data-data sejarah, kita akan mengerti bagaimana Celan sebenarnya sedang menyajikan alam kematian, absurditas dan kegelapan hidup di bawah bayang-bayang Nazi. Segala perlambang dalam sajaknya itu bisa ditelusuri ke riwayat pribadinya sebagai penyintas Holocaust—bahkan ke sejarah dan konteks di mana puisi itu dilahirkan. Meskipun, pembacaan yang seperti ini punya resiko besar, yakni puisi pada akhirnya seolah-olah punya satu rujukan dengan makna yang tetap nan stabil; sebuah kerja-kerja representasionalisme yang mengaitkan semesta sajak pada sembarang hal di luar teks. Hal demikian ini, pada akhirnya, punya efek samping mengerdilkan percikan isyarat.
Membaca buku Royyan juga punya cita rasa yang sama. Kita bisa membacanya dengan atau tanpa dokumen dan arsip sejarah. Di tulisan ini, kita akan mengerjakan dua-duanya, tanpa harus menganggap tulisan ini sebagai kerja-kerja representasionalistik.
***
Bagaimana rupa tafsir melingkar itu digarap dalam puisi? Marilah, mula-mula, kita cermati sehimpun sajak ini dari segi struktur internal—beserta sembarang konsekuensinya.
Pertama, Uroboro Syekh Kholil Bangkalani tentulah sebuah puisi modern. Watak puisi modern jelas belaka: ia tidak teguh memegang prinsip rima, irama dan bentuk yang tetap. Jika kita melihat kelahiran puisi modern, ia dibidani oleh usaha untuk melampaui tradisi puisi romantik dan victorian. Dalam tradisi romantik, puisi terlalu disesaki hal-hal yang sentimentil dan dipenuhi kerinduan akan alam; adapun dalam tradisi victorian, disesaki oleh petuah-petuah moral—singkatnya, puisi didaktik. Puisi modern berlaku tidak demikian, ia seringkali absurd dan terfragmentasi (kita bisa melihat ciri fragmentasi ini di dalam puisi modernis awal, untuk mengutip dua contoh, T.S. Eliot dan Ezra Pound). Dan, fragmentasi inilah watak selanjutnya dari puisi modern itu.
Terkait watak fragmentasi, bisa kita nukil bait ke-3 dan ke-4 “Tarekat Nabi Khidir” berikut:
Suara itu membujur
dari waktu yang bersirip karat
dan ruang yang menjadi amis.
Tetapi kekal adalah sepatah
yang pejal dan tak berperasaan
Di bait ke-3 dan ke-4 tidak ada alur naratif, melainkan benturan imaji belaka. Dan, dari benturan itulah justru yang memungkinkan makna menyembul ke permukaan. Terdapat sebuah perpindahan yang serba tiba-tiba antara suara, citra, dan imaji. Perpindahan tiba-tiba itu membuat pembaca kaget, dan persis di situlah estetika puisi modern terletak. Di sekujur tubuh buku puisi ini, kita bisa menemukan bagaimana fragmentasi yang seperti itu hadir secara intens.
Baiklah, mari kita bandingkan dengan sajak singkat Ezra Pound, “In a Station of the Metro” berikut: “The apparition of these faces in the crowd; / Petals on a wet, black bough.” Di dua baris sajak ini terdapat dua jukstaposisi imaji (wajah manusia dan bunga basah) yang saling merangkai tanpa ada jembatan apa pun. Fragmentasi ini menjadi, katakanlah, tonggak ciri puisi modern. Di Indonesia, sudah jelas ciri itu melekat betul dalam sajak-sajak Chairil Anwar. Dan Royyan, berada di koridor sanad puisi modernis
yang memegang teguh situasi fragmentaris seperti itu.
Sejarah yang diolah melalui fragmen-fragmen imaji membawa kita ke sebuah situasi yang khas. Situasi di mana sejarah dialami sebagai suasana dan, bahkan, sebagai ironi. Sebuah sejarah yang tidak patuh pada ketentuan sejarah yang-wajar; di mana kronologi atau rentetan waktu hilang dan yang tersisa semata-mata suasana. Dengan demikian, jika ilmu sejarah mengonstruksi rentetan peristiwa, sajak-historis mengonstruksi suasana.
Sejarah sebagai suasana itu terjadi sebab Royyan dalam buku ini mengolah sejarah melalui puisi lirik. Apa itu puisi lirik? Singkatnya, puisi lirik itu puisi suasana. Artinya, diksi “mendung” misalnya, diksi tersebut kurang lebih bermain-main dengan suasana rawan di sekitar “mendung”: gelap, murung, sedih, nanar, dll. Dengan demikian, persis seperti skema puisi lirik, Royyan bermain-main dengan suasana yang rawan di sekitar sejarah, kultur, dan legenda Madura.
Ciri puisi lirik—yang juga berada dalam satu rangkaian puisi modern—penuh dengan keharuan dan meledak-ledaknya alam batin sang penyair. Coba kita periksa sajak-sajak Chairil Anwar dalam sajak “Aku”, “Krawang-Bekasi”, “Pemberian Tahu”, misalnya, tiga contoh sajak ini berangkat dari keharuan—atau sekurang-kurangnya persepsi—penyairnya terhadap sebuah situasi tertentu. Mustahak jika sajak lirik seringkali menggunakan sudut pandang orang pertama untuk mengawal imajinasi.
Dan, Royyan berada di persimpangan. Sajak-sajaknya berwatak lirik, tapi bukan sepenuhnya suara aku-lirik si penyairnya. Bisa dikata, sajaknya merupakan lirisisme intelektual. Liris karena di sekujur buku ini Royyan intens menggunakan sudut pandang orang pertama; pemenggalan baris demi efek liris; ketakpatuhan seratus persen pada rima; metafora yang tetap mempertimbangkan bunyi; dan imaji sekaligus irama patah. Namun, suara aku-lirik dalam sajak bukanlah suara si penyair, melainkan suara sejarah yang telah disuling melalui kerja tafsir melingkar; dan persis di situ ia intelektualistis. Oleh karenanya, seperti yang kita singgung di muka, aku-lirik dalam Oroboro Syekh Kholil Bangkalani goyah dan ambigu, tak lagi ada batas antara suara sejarah dan si penyair. Suara keduanya saling sahut-menyahut.4
Hal ini mengingatkan kita pada gaya ungkap sajak “Pariksit”, “Interlude”, atau “Asmaradana” karya Goenawan Mohamad. Betapa jika kita menyanding bandingkan Goenawan dengan Royyan, kita akan melihat begitu dekat ciri estetika keduanya. Bandingkanlah, misalnya, sajak “Menjelang Pembakaran Sita” karya Goenawan dengan “Elegi bagi Pasean yang Bingung” karya Royyan. Atau dalam sajak “Malam Kedua” di bait ke-5: “Barangkali nasib bisa dikendalikan / dengan tali dan sanggurdi.” Sajak Royyan ini mengingatkan kita pada sajak “Jembatan Karel”, “Praha” di bait terakhir karya Goenawan: “Lupa memang tema kita, akhirnya. / Tahun menggerakkan tali. Dan kita menari.” Kedua sajak ini, baik dari segi mengolah frasa, klausa, atau kalimat, metafor maupun bunyi, menghadirkan suasana yang mirip.
Selanjutnya, hal menarik yang patut kita tandai adalah penggunaan personifikasi. Dengan intens sajak-sajak Royyan dalam buku ini memberlakukan personifikasi: “Dari rahim gua…”; “Di angkasa yang masygul…”; “zakar bulan…”; “Ketuban laut pecah…”; “biji-biji yang berikrar / kepada pagi:…”; “Di curam punggung Juni…”; “kelenjar bulan…”; “Bokong malam…”. Personifikasi, kita tahu, sebentuk kerja-kerja meniupkan ruh manusiawi ke alam benda.
Aktivitas meniupkan yang manusiawi ke alam benda ini membuat sesuatu yang tampak mustahil jadi sesuatu yang wajar. Alhasil, apa-apa yang tak terduga dan asing jadi muncul sekaligus akrab. Di hadapan bahasa personifikasi itulah terdapat semacam efek kejut; dan dari efek kejut itu lah apa-apa yang-indah bisa dialami. Di sisi yang lain, personifikasi memperluas kerja-kerja penafsiran. Tafsir meluas sebab personifikasi membubuhkan konotasi baru terhadap sesuatu yang dilekatinya. Misal, untuk menukil satu contoh, di bait terakhir sajak “Kelahiran Pangeran Segara” berikut:
Ketuban laut pecah dan membiakkan
kasta kesatria yang akan menaklukkan
badai di rahim ibunya
Personifikasi ketuban laut pecah menyebabkan sebuah konotasi baru dalam keseluruhan tubuh sajak: yakni konotasi kosmogoni dan heroik (di mana laut mengisyarat pada mitos penciptaan, sekaligus isyarat kepada dimulainya sebuah era baru). Kerja-kerja meniupkan ruh pada jisim benda ini membuat puisi melenturkan dan memperluas tafsir. Persisnya, sang penyair dengan sadar membiarkan semua kemungkinan medan resonansi dan asosiasi citraan berkelindan liar. Dan, keliaran medan resonansi dan asosiasi citraan inilah sebab musabab tafsir jadi meluas dan melentur ke berbagai arah.
Selain siasat citraan dan/atau imaji, menyigi bobot bunyi juga satu hal yang tak terhindarkan. Karena seringkali majas-majas dalam puisi, selain untuk menghadirkan efek kejut dan benturan antar imaji, juga digunakan untuk mengolah musikalitas. Dalam Oroboro Syekh Kholil Bangkalani, musikalitas bunyi diolah tidak dalam bentuk langgam klasik. Sebagai contoh, kita kutip utuh sajak berjudul “Tirtanagara & Saot” berikut:
Malam itu Hujan memeluk
dan berbisik di tengkuknya,
“Letakkan takhtamu
di pundakku.”
Peluh menggenangi ranjang
dan dari celah jendela,
guruh menyiulkan sebuhul nama
Inkubus…Inkubus…Inkubus…
Dan fajar menetes
di kedua pahanya.
Maka, sebuah kereta turangga
melesat ke arah sabana
dan wanita itu berlutut
di hadapan Mimpi,
“Kutanggalkan kehormatanku
di hadiratmu, Tumenggung.”
“Bukan Tumenggung, Denayu.
Hamba hanya pria gembala
yang ditunggangi bini
dan anak-anaknya.”
Tetapi ia berkata-kata,
“Tidak, Tumenggung.
Kau iblis jantan yang menetakkan
maut di leherku malam itu
maut di leherku malam itu.”
Metrum atau suku kata dalam sajak ini bernuansa irregular. Baris-baris sajak cenderung memiliki jumlah suku kata bervariasi. Misal di pembukaan sajak, “Malam itu Hujan memeluk” terdiri dari 9 suku kata; “dan berbisik di tengkuknya” terdiri 8 suku kata. Irregularitas membuat sajak ini terbaca dengan ritme napas yang tak terduga. Ditambah dengan pemenggalan baris yang digunakan untuk menunda resolusi bunyi, entah bertujuan menjeda atau menunda arti. Hal ini jelas berbeda dengan langgam lama yang skema sajaknya terikat pada pola metrum klasik yang serba terukur (misal syair, pantun, soneta, atau bahkan memperhitungkan iambik pentameter yang menjadi ciri khas puisi lama). Bunyi tak patuh pada kaidah rima akhir dan tak konsisten pada satu bentuk tertentu. Lagi-lagi, ketakpatuhan pada rima, irama, dan bentuk—yang menjadi ciri dari puisi modern—mempertegas posisi Royyan dalam rentang sejarah puisi Indonesia.
Di sisi lain, fungsi rangkaian bunyi dalam sajak ini jelas: bahwa bunyi menjadi wahana jejaring simbolik agar konflik-tema dalam sajak “Tirtanagara & Saot” bisa dipetakan. Misal suara nasal /m/, yang menggambarkan bagaimana keintiman, tubuh, dan kelahiran bisa diikat ke dalam tema kehangatan yang mengancam. Atau suara plosif /t/, /k/, dan /p/ di awal bait yang mempertegas situasi kekerasan atau mandat otoritas. Singkatnya, antara bunyi dan imaji saling mengait satu sama lain untuk menghadirkan suasana tertentu—dalam konteks sajak ini, suasana yang mengancam, intim, epik, sekaligus mistik.
Di dalam sajak tersebut, kita juga bisa melihat ada sebuah repetisi: “Inkubus…Inkubus…Inkubus…” dan “maut di leherku malam itu / maut di leherku malam itu”. Repetisi ini mengingatkan kita pada puisi mantra Sutardji Calzoum Bachri di O, Amuk, Kapak.5 Ciri utama dari mantra adalah pengulangan, repetisi tak henti-henti. Namun, Royyan tak hendak mengentalkan mantra ke keseluruhan tubuh sajak. Ia hanya menyelipkannya di tengah dan akhir. Artinya, gaya mantra digunakannya setengah hati. Meski demikian, repetisi dalam sajak ini mengisyaratkan bahwa Royyan—di tengah dan akhir sajak—hendak menggeser imaji ke bunyi. Tidak hanya di sajak Tirtanagara & Saot, di sajak lain, misal di “Sayyid Ahmad Baidawi”, “Tanjung Sekar”, “Syekh Tanah Merah”, “Sebuah Tangisan Malam di Kota Syahbandar”, “Suluk Daun Kencana”, “Solilokui Bukit Kapur”, dan “Gadis yang Menggoda Adirasa di Sebuah Bar”, juga memiliki kualitas repetisi yang menyaru mantra.
Royyan menggunakan ciri mantra ini bukan untuk membebaskan kata dari kekangan kamus, atau membuat kata tak lagi menjadi alat mengantarkan pengertian; melainkan sebagai gejala untuk mempertegas bunyi, imaji, dan suasana dalam sajak.
Perihal bunyi, terdapat satu hal yang patut disinggung, yakni onomatope atau sandi sora di sajak “Di Museum Mandhilaras”. Kita tahu, onomatope atau sandi sora merupakan sekelompok kata yang meniru bunyi dari sumber yang digambarkannya. Misal kata “detak” meniru bunyi “tak” dari jantung; atau “detik” yang meniru bunyi “tik” dari arloji. Kualitas sandi sora yang demikian juga tampil dalam bait berikut:
Di situlah mataku, mata Ibnu
juga Niar dan sepuluh jari ibu
menyibak lubang sesak
bagi Fauzi dan kuda lari
Pak-ketepak-ketepak-ketepak!
Fungsinya hampir sama seperti ciri mantra yang telah kita singgung: memperkuat bunyi dan imaji dalam sajak. Namun, bagi saya, onomatope memiliki sebentuk fungsi yang teramat khas, yakni membawa kita mendengar dunia yang hendak digambarkan; tidak semata-mata membayangkan gambaran dunia itu. Dalam kasus sajak “Di Museum Mandhilaras” ini, kuda lari itu dapat terdengar dan membuat kita mampu menguping, secara auditif, semesta dunia yang disampaikan di bait pertama.
***
Saatnya kita akan mencoba membaca salah satu sajak dalam Uroboro Syekh Kholil Bangkalani melalui daya dukung hipogram. Sajak yang termaksud adalah Uroboro Syekh Kholil Bangkalani itu sendiri yang menjadi judul buku:
Ular yang kauserahkan kepadaku
menelan ekor waktu
dan membuhul bumi
dengan sembilan bintang
yang berpijar dari Gurun Paran
Ya Jabbar, ya Qahhar…
Sang Perkasa dan Memaksa,
kuhidangkan lima sisik ayat-ayat Taha
di piring orang-orang lapar.
Dan binatang itu membisikkan
isim di telinga musim,
“Jadilah baka
seperti asma-Nya.”
Lalu kemarau yang berderak
di tulang-tulang batu menjadi hijau.
Sehijau nama-Mu
Pertama, izinkan saya menyampaikan sebuah alkisah. Sebuah kisah yang, sebenarnya, dihantar melalui transmisi lisan dan sedikit dokumen historis yang mendukungnya. Segala penjabaran kisah ini—tanpa memperkarakan validitas dan keabsahannya—saya ambil langsung dari pengakuan sang pelaku sejarah: Kiai As’ad Syamsul Arifin.6 Alkisah, di akhir tahun 1924, oleh Kiai Kholil Bangkalan, Kiai As’ad diberi satu mandat penting untuk menghantar sebuah tongkat dan tasbih ke Keras, Jombang, ke kediaman Kiai Hasyim Asy’ari. Kiai Kholil memberikan uang satu sen sebanyak tiga kali sebagai ongkos jalan menghantar tongkat dan tasbih itu. Lalu, ujung tasbih itu dipegangnya, dikibas-kibas, lalu diisimkan Ya Jabbar, Ya Qahhar bergantian selama satu putaran tasbih sebelum dikalungkan ke leher Kiai As’ad. Juga tongkat, sebelum diserahkan kepada Kiai As’ad, dibacakannya lantang-lantang Surat Thaha ayat 17-21. Singkat cerita, dua barang keramat itu sampai ke Keras, dan Kiai Hasyim akhirnya menerima pesan Kiai Kholil perihal isim dan lima sepenggal ayat tersebut. Kita tahu, pertemuan ini, konon, menjadi cikal-bakal lahirnya organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama.
Sejarah tersebut akan menjadi koridor untuk membaca perlambang-perlambang yang ada di dalam sekujur sajak. Dengan demikian, jika kita berpedoman pada hipogram sejarah tersebut, maka sajak Uroboro Syekh Kholil Bangkalani ini aku-liriknya adalah Kiai As’ad. Kita kutip bait pertama:
Ular yang kauserahkan kepadaku
menelan ekor waktu
dan membuhul bumi
dengan sembilan bintang
yang berpijar dari Gurun Paran
Ular di sini jelas simbol bagi tasbih. Persisnya, ular yang melilit dan menelan ekornya sendiri, kita tahu, juga menunjuk pada simbol ouroboros yang menjadi tajuk jadul. Simbol ouroboros sudah ada lama sekali, ia setidaknya telah muncul di abad ke-14 SM di makam Tutankhamun. Ular yang menggigit ekornya sendiri itu, menjadi figur atau nama lain dari keabadian dan Yang-Satu. Persis di sini, tasbih diibaratkan sang penyair melalui ouroboros. Oleh karenanya, kita bisa membaca judul sajak ini demikian: Tasbih Syekh Kholil Bangkalani. Dengan skema daya dukung hipogram seperti ini, alhasil bait-bait selanjutnya pun jadi terasa sangat masuk akal.
Di awal pembukaan sajak, makna perlambang terasa hadir sebagai paradoks. Ular, ouroboros dan tasbih saling mengunci, saling merujuk satu sama lain; tapi pada saat yang sama, juga saling mengurai. Ular yang dimaksud menunjuk pada simbol ouroboros, dan simbol ouroboros menjadi perlambang lain untuk tasbih. Dan, tiga diksi ini memiliki makna yang saling mengunci, yakni ketiganya sama-sama menjadi isyarat bagi keabadian, kekuatan adimanusiawi, dan infinity loop (ketakhinggaan). Namun, pada saat yang sama, tiga atribut tersebut saling mengurai: ular dalam Surat Thaha, misalnya, menjadi subjek kunci dalam peristiwa pertemuan Musa dan Tuhan; di seberang lain, ular jadi metafor untuk tasbih yang diberikan Kiai Kholil kepada Kiai Hasyim melalui perantara Kiai As’ad; dan di seberang lainnya lagi, ular ouroboros menjadi simbol harapan agar Nahdlatul Ulama jadi abadi yang tampak dalam larik ini: “Dan binatang itu (baca: ular; tasbih—pen) membisikkan / isim di telinga musim, / “Jadilah baka / seperti asma-Nya.” Mustahak jika kita mengatakan ular, ouroboros, dan tasbih menjadi lelambang yang saling mengunci, tapi pada saat yang sama saling mengurai. Di lirik ini pula terasa bagaimana tafsir melingkar Royyan bekerja: ia menafsirkan bahwa lafalan Ya Jabbar Ya Qahhar, adalah mantra agar organisasi hijau itu jadi langgeng-abadi, jadi baka.
Oleh karenanya, tasbih—jika kita setia pada hipogram sejarah—jadi isyarat terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun larik “membuhul bumi dengan sembilan bintang” menggambarkan dengan terang logo Nahdlatul Ulama. Dari awal hingga akhir bait, sajak ini terasa hendak menggambarkan elan vital proses berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama itu: “Lalu kemarau yang berderak / di tulang-tulang batu menjadi hijau. / Sehijau nama-Mu”.
Namun, bagi saya, hal paling menarik justru ada di larik terakhir bait pertama: “yang berpijar dari Gurun Paran.” Larik ini menunjuk dan merujuk dengan jelas pada kandungan isi Surat Thaha 17-21 yang menceritakan pertemuan Musa dengan Tuhan. Namun, pada saat yang sama, latar Gurun Paran diambil dari Alkitab. Sebab, Alquran tidak menyebut terang benderang di wilayah mana Musa dan Tuhan bertemu.
Gurun Paran, yang bisa kita baca di kitab Kejadian 21:19-21 dan Bilangan 10:12, merupakan tempat bangsa Israel menetap setelah keluar dari jazirah Mesir. Di ayat Bilangan 12:16, Gurun Paran juga disebut sebagai tempat bangsa Israel berkemah setelah peristiwa Miriam dihukum kusta. Di sisi lainnya, Gurun Paran ini juga akrab dikenal sebagai Nubuat Tiga Gunung, sebab tiga risalah besar Tuhan (Taurat, Injil, dan Quran) turun. Benar, sebuah wilayah jouissance tempat nabi-nabi mendengar bisik Tuhan.
Royyan di bait pertama ini, terasa seperti seorang pengembara kitab suci; berjalan zigzag di antara dua lembah khazanah. Ia memakai latar dalam Alkitab untuk menjelaskan tempat peristiwa di Surat Thaha. Jelaslah jika puisi, hemat saya, jadi tempat elastis di mana pertemuan dua khazanah—yang seringkali bentrok dan tak nyambung—bisa saling merangkai, menjadi titik temu yang memperluas khazanah satu sama lain. Puisi sebagai tempat arus transmisi, tempat di mana apa-apa yang belum berdialog bertemu dan memulai perbincangan. Sebab bait pertama ini, Royyan tampak menjelma jadi seorang ahli kitab; orang-orang yang berpegang tidak hanya pada satu risalah Tuhan.
Sebuah pertemuan berbagai cara pandang dunia: berbagai khazanah yang berlainan bertemu dalam satu tubuh sajak. Hal ini juga tampak, misal, di sajak Oedipus Complex, di sana-sini kita akan merasakan bagaimana khazanah Alkitab juga merangsek masuk ke dalam khazanah Islam.
Toh, satu yang harus kita ingat, Uroboro Sykeh Kholil Bangkalani juga bisa dibaca selain pembacaan ini. Puisi selama-lamanya dikutuk agar arus pemaknaan tak selalu menuju ke satu muara. Sajak Royyan ini pun pada akhirnya bisa dibaca jua tanpa daya dukung hipogram, bahkan maknanya juga bisa dicungkil tanpa harus membaca traktat sejarah. Artinya, “membuhul bumi / dengan sembilan bintang”, misalnya, tidak melulu ditafsir sebagai logo Nahdlatul Ulama. Makna sebuah sajak tak bisa dikunci. Puisi, toh, bisa dibaca dengan atau tanpa konteks. Justru di situ puisi hidup-terus, la survie. Kita harus bisa membayangkan sajak ini—sembarang sajak barangkali—keluar dari penjara historisisme dan kerja-kerja representasionalisme. Tapi bagaimanapun, ini masihlah sebentuk hipotesa.
***
Saya akan menutup tulisan ini dengan menukil kalimat penutup The Death of the Author karya Roland Barthes:
“…kita tahu bahwa untuk mengembalikan masa depan pada tulisan, kita harus membalik mitosnya: kelahiran pembaca harus ditebus dengan kematian Pengarang.”
Di tulisan ini barangkali bukan hanya Royyan yang telah tamat, tapi juga sejarah.
- Di sini saya cukup memakai kata “sejarah” untuk merangkum segala aktivitas di masa lalu, baik bersifat personal maupun komunal. Sejarah di sini saya pakai dalam artinya yang paling luas.
↩︎ - Puisi-historis yang sekadar menjabarkan suatu peristiwa tertentu, tanpa berusaha menafsirkannya, yang terdengar hanya suara sejarah belaka. Si penyair jadi mulut sejarah dan jikapun ada intervensi sang penyair, itu bertujuan menjabarkan sejarah jauh lebih terang. Puisi Paul Celan, misalnya, yang berusaha menyajikan kekelaman kamp konsentrasi melalui sudut pandang dan rasa sakit personal, justru mempertegas sejarah kengerian Nazi yang diliputi total kegelapan itu. Royyan tak hendak semata-mata menegaskan atau menggambarkan sejarah, justru juga memuntirnya, menafsirkannya. Royyan dalam buku ini bekerja dalam sebuah jarak untuk menampilkan sejarah yang bersifat subjektif, bukan sejarah objektif yang syarat dengan aturan-aturan kronologis.
↩︎ - Lihat esai T.S. Eliot “The Metaphysics of Poetry”. bisa diakses di laman https://www.uwyo.edu/numimage/eliot_metaphysical_poets.htm
↩︎ - Puisi lirik Royyan yang membuncah-buncah mengungkapkan alam batinnya itu, yang juga bisa dikatakan aku-liriknya adalah si penyair, ada di buku Ranjang Poskolonial.
↩︎ - Sutardji Calzoum Bachri. O Amuk Kapak. Jakarta: Sinar Harapan. 1981 ↩︎
- Penyampaian Kiai As’ad ini saya ambil dari sini: https://www.youtube.com/watch?v=jB_oN91Uvo4 dan https://www.youtube.com/watch?v=ZlO1_xgiSWU&t=360s ↩︎
R.H. Authonul Muther adalah Direktur Edisi Mori.
Editor: Putri Tariza