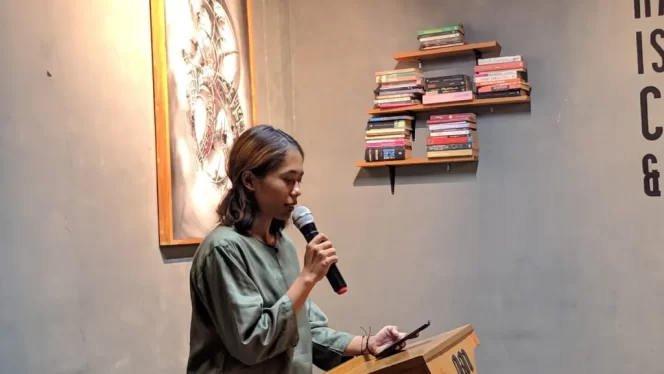Saya menyebutnya rumor. Rumor yang diceritakan terus-menerus sampai kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan rekaan. Isu yang serupa tali, melilit tubuh kita sampai tak bisa berkutik. Bertahun-tahun gunjingan itu bertahan, serupa tembok. Hingga suatu hari, saya mesti membenturnya.
Begitulah rumor tentang perempuan yang seolah tak punya banyak pilihan. Konon, wanita tak elok jika keluar dari ranah kasur, dapur, dan, sumur. Bukan tidak boleh. Tak elok dalam tradisi Madura merupakan eufemisme sehingga kita bisa saja bertanya atau menafsir satu perkara yang disebut demikian. Ketakpatutan menjadi belenggu bagi tubuh perempuan. Seperti ketidakelokan dalam memilih gaya berpakaian, riasan, atau profesi.
Batasan semacam itu saya kira tidak hanya berlaku di Madura. Mungkin juga di Jawa, atau kalau kita baca perihal nasib perempuan dalam berbagai kebudayaan, terlalu banyak tidak eloknya. Kalaupun ada sesosok wanita yang tampil beda, kita sering membuat pengecualian. Satu banding seribu. Atau kita acap terjerumus pada asumsi-asumi feodal: hanya perempuan-perempuan tertentu yang boleh melanggar yang tak elok. Lalu, bagaimana jika perempuan jadi pandai besi? Menjadi seorang pembuat senjata? Pencipta keris yang masyhur dengan maskulinitasnya? Apakah wanita tak pantas menjadi empu? Benarkah perempuan berjarak dengan keris dan pusaka?
Menjadi seorang empu tak hanya berurusan dengan besi. Tidak pula soal pamor dan magi pusaka belaka. Seorang empu juga kudu mampu menerjemahkan berbagai “tanda” yang datang. Menafsirkannya menjadi anasir-anasir yang menggerakan daya hidup.
Bagi seorang empu, keris merupakan pusaka sekaligus anak kandung. Sebagai pusaka, ia layaknya titik pusat kehidupan tak kasat mata dengan pancaran aura optimisme, yang mampu melahirkan energi positif, atau kedigdayaan dalam memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu, keris seringkali menjelma simbol kekuasaan. Keris menjadi raga sekaligus roh sang pemilik. Lalu, keris diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika puisi dan novel menyimpan semangatnya dalam satu rangkaian cerita dan jalin-kelindan konflik tokoh-tokohnya, keris menangkap semangat zaman dari pamor serta aura keagungannya.
Maka, tak heran jika teks Asmarandana, sastra suluk yang memberi perumpamaan mengenai keris dan sarungnya menjadi bentuk kisah kemanunggalan manusia dan tuhannya. Atau sering pula disebut sebagai simbol laki-laki dan perempuan, lingga–yoni. Dalam falsafah Jawa, simbolisasi maternal-paternal melekat pada alat yang digunakan pandai besi dan pembuat keris. Paron (besi landasan tempa) dianggap lambang bumi atau ibu lantaran berada di bawah dan statis tertanam di tanah. Sementara itu, palu yang kinetis adalah simbol angkasa atau unsur maskulin.
Unsur pembuat keris juga tak lepas dari perlambang produk kosmis, antara bahan yang berasal dari bumi sebagai ibu atau elemen maternal dan bahan yang berasal dari angkasa (besi meteorit) sebagai ayah atau anasir paternal. Keseimbangan dua sisi inilah yang seharusnya menyadarkan kita tentang perlunya mendobrak paradigma bahwa keris hanya milik pria seperti yang selama ini seolah menjadi kesepakatan masyarakat.
Sejarah panjang tentang keris nyatanya tidak pernah alpa dari peran wanita. Mulai kisah Dewi Madrim yang memiliki keris dengan pamor bendo sagodo yang sampai detik ini menjadi idola para penyuka keris hingga cerita para empu perempuan perajin keris era Pajajaran yang kerisnya tak kalah populer dari keris Empu Gandring.
Bukan perkara gampang saat saya memutuskan untuk menekuni warisan leluhur sebagai empu. Pertama, saya harus menjawab: Apa saya sanggup membuat keris? Apa saya paham kualitas besi? Apa saya bisa membuat pamor? Kedua, saya harus mampu meyakinkan orang-orang sekitar bahwa pilihan menjadi seorang empu bukan sekadar mewarisi tradisi leluhur. Lebih dari itu, saya perlu menegaskan bahwa profesi ini saya pilih sebab saya mencintai seni pembuatan keris. Karena saya punya obsesi bahwa hidup saya ditakdirkan untuk bergelut dengan pamor dan lekuk yang molek. Bahwa saya punya cita rasa untuk setiap pusaka.
Setelah beberapa tahun menjadi seorang pembuat pusaka, usai bergelut dengan diri sendiri dan melakukan pembacaan ulang soal perempuan dalam jagat keris, tidak lantas membuat saya lepas dari rumor ketidakelokan. Ada banyak predikat yang saya sandang seperti sebutan lalake’a burung (urung jadi lelaki) yang bagi pemahaman dan penerimaan saya berarti menyeberang kodrat seorang wanita yang seyogyanya tidak berada di posisi yang memiliki kemampuan setara dengan pria. Sebuah pengerdilan atas apa yang saya tekuni dan yakini.
Gunjingan yang dilontarkan itu seperti batu. Omongan yang menghunjam, merobek, dan mengoyak kesetaraan orang dalam menikmati hidup. Suatu ketika, seseorang pernah bertanya kepada saya: Jika perempuan menjadi empu, apakah keris yang akan dibuat dijepit di antara pahanya seperti kisah pembuatan keris Mbok Sombro, empu perempuan era Majapahit silam? Jika perempuan menjadi empu, apakah keris yang dilahirkan hanya besi berpamor semata? Perkataan macam itu tidak bisa tidak mengusik. Empu perempuan hanya dipandang sebagai perlambang tubuh yang berbeda, yang lebih menggairahkan jika melibatkan sisi erotisnya.
Saya kadang kesal karena dalam setiap perjumpaan, hal pertama yang menarik untuk diperbincangkan dari diri saya ternyata adalah jenis kelamin saya. Saya menjadi episentrum obrolan bukan lantaran saya punya karya yang layak diperbincangkan. Saya diundang di forum-forum karena keasingan pilihan hidup saya. Saya menjadi seksi sebab saya satu-satunya perempuan di antara lelaki.
Tak ada pilihan hidup yang salah. Selagi kita mencintai dan memahaminya, pilihan yang kita buat bakal menuntun kita untuk memahami makna hidup serta mereguk manis kehidupan. Pun pilihan menjadi empu telah membuka jalan yang tak pernah saya sangka selama ini. Ketekunan saya menggerinda lambat laun membawa saya pada titik di mana saya dapat bertemu banyak orang dan mengunjungi berbagai kota di Indonesia. Saya diajak pameran dan diminta bercerita ihwal bagaimana keris lahir serta tumbuh sebagai anak kandung yang saya cintai.
Pada akhirnya, seorang empu, terlepas dari alat genital yang melekat pada tubuhnya, pasti ingin dikenal lantaran karyanya, karena keris-keris yang dilahirkannya benar-benar bertuah dan pamor ciptaannya mengundang decak kagum. Seperti Empu Ranu Baya dalam serial radio Tutur Tinular, atau Pramoedya Ananta Toer yang tak habis dikenang karena tetralogi Buru-nya, atau Chairil Anwar yang namanya tak henti disebut berkat puisi “Aku”.
Kita memang tidak bisa lepas dari dikotomi laki-laki-perempuan, baik-buruk, bagus-jelek. Dualisme macam itu adalah keniscayaan. Namun, pada tataran yang lebih transparan, cara pandang demikian hendaknya tidak menjerumuskan kita pada simpulan-simpulan prematur. Kini, saya menyadari, berbagai isu yang melilit tak perlu saya lawan atau enyahkan. Ia akan bertahan seiring roda zaman. Rumor yang satu akan berganti yang lain. Satu-satunya hal yang mesti saya pastikan yakni bahwa keris, sebagai warisan leluhur, harus lestari. Ia kudu tetap menjadi “roh lain” kemanusiaan kita.
*Tulisan ini disajikan sebagai Pidato Kebudayaan Dies Natalis ke-6 Sivitas Kothèka.
Ika Arista adalah empu keris dari Sumenep.
Editor: Asief Abdi