Puluhan orang memadati kafe balada pada pembukaan festival sastra-sains 2025 sekaligus Koloman Budaya ke-102 Sivitas Kothèka, Sabtu 13 September lalu. Festival tahun ini mengangkat tema “Epistemologi Maut dan Cinta”. Tema tersebut dipilih lantaran maut dan cinta tak pernah lepas dari karya sastra, dari Gilgamesh hingga Cantik Itu Luka. Keduanya dianggap paradoks yang sering kali melebur dan tak terpisahkan—Eros dan Thanatos.
Festival Sastra Sains merupakan lanjutan dari gelaran tahun lalu yang bertajuk “Galahku Janur Kuning”. Sivitas Kothèka berharap festival ini bisa menjadi agenda tahunan. Pada tahun ini, festival ini didukung oleh oleh program Penguatan Komunitas Sastra yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan RI, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Mahendra, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, bahwa program Penguatan Komunitas Sastra ini adalah upaya untuk menjembatani antara karya sastra dengan pembaca. Karena selama ini, diseminasi buku sastra masih belum optimal. Komunitas sastra berperan sebagai ujung tombak yang akan menyebarluaskan karya sastra, dengan cara mendiskusikannya dan mengalihwahanakannya.
Festival Sastra Sains 2025 berlangsung dari tanggal 13 hingga 28 September 2025 dengan serangkaian persembahan menarik. Acara dibuka dengan penampilan musik oleh Svara Sivitas. Lagu yang mereka lantunkan yaitu “Aku Ingin”, sebuah musikalisasi puisi Sapardi Djoko Damono yang dipopulerkan duo Ari-Reda. Acara dilanjutkan dengan prolog oleh ketua pelaksana, Wardedy Rosy. “Letakkan daku seperti meterai di hatimu, serupa meterai di lenganmu. Sebab, cinta kuat bagai maut, berahi teguh seperti dunia orang mati, nyalanya adalah kobar api, laksana gelora api Tuhan!” katanya mengutip Kitab Kidung Agung. Lalu, festival resmi dibuka secara simbolik dengan tabuhan rebana oleh mahasiswa Unira itu. Tepuk tangan meriah, acara resmi dimulai.


Lalu, tiba gilirannya untuk mendengar pidato kebudayaan. “Dari Evolusi Cinta Plato hingga Evolusi Kematian Rumi: Eros dan Thanatos sebagai Jalan Pengetahuan” adalah judul ceramah yang akan disampaikan Nyai Fadhilah Khunaini. Dia merupakan dosen filsafat di Universitas Annuqayah, Sumenep. la menyelesaikan kuliahnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid, Paiton, dan melanjutkan studi magister filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Menurut sang Nyai, epistemologi atau teori pengetahuan, menjadi sangat eksistensial ketika dihubungkan dengan maut dan cinta. “Pengetahuan bukan sekadar tentang ‘apa’, melainkan ‘bagaimana’ maut dan cinta itu sendiri,” Kata beliau. Ia membedah bahwa filsafat cenderung menjawab pertanyaan pertama, sedangkan mistik akan menjawab yang kedua. Ini menyoroti bagaimana dua pengalaman paling universal dalam hidup manusia dapat menjadi panduan menuju pemahaman akan eksistensi.

Beliau menekankan bahwa cinta sejati bukanlah untuk memiliki, melainkan untuk memberi. Ia mengutip pemikiran Erich Fromm, seorang psikoanalis humanis, yang melihat cinta sebagai keterampilan yang harus dilatih seumur hidup. Hal ini diibaratkan seperti seorang pelukis yang tidak melulu mencari objek indah, tapi juga cara mengasah objek yang dilukis menjadi indah.
Cinta dan maut sering kali dianggap paradoks, namun Fadhilah Khunaini berpendapat bahwa keduanya saling melengkapi. “Mencintai yaitu merangkul sampai tiada,” ujar dosen filsafat itu, menggarisbawahi bahwa cinta sejati melampaui batas-batas kehidupan fisik dan terus hadir bahkan dalam menghadapi ajal. Di pengujung pidatonya, beliau menyampaikan pesan penutup dari pemikiran Derrida, “Mencintai berarti merangkul sesuatu yang suatu saat akan tiada,” sebuah kalimat yang merangkum ironi antara maut dan cinta sebagai jalan pengetahuan.
Sekarat dan Rindu Dendam Uroboro
Rangkaian Festival Sastra Sains kembali berlanjut dengan Koloman Budaya ke-103 yang masih digelar di Kafe Balada pada Rabu, 17 September 2025. Acara kedua dari festival ini menghadirkan sesi bincang buku dan gagasan yang mendalam bersama penulis R.H. Authonul Muther, yang membedah buku puisi Uroboro Syekh Kholil Bangkalani karya Royyan Julian.
Dipandu oleh Ikrar Izzul Haq sebagai moderator, diskusi berpusat pada bagaimana puisi modern berdialog dengan sejarah. R.H. Authonul Muther—akrab disapa Ririd—adalah penulis buku “Akhir Sentuhan” (2022) sekaligus direktur penerbit Edisi Mori dan pendiri komunitas sastra Operasi Senyap Sarajevo. Lulusan Universitas Muhammadiyah Malang itu dikenal dengan esai-esai filsafat dan kritik sastranya di berbagai media. Dalam paparannya, Ririd menjelaskan bahwa puisi dalam buku Royyan memiliki kemampuan untuk “menggoda” sejarah, bukan sekadar mencatatnya dalam narasi yang beku dan tunggal.
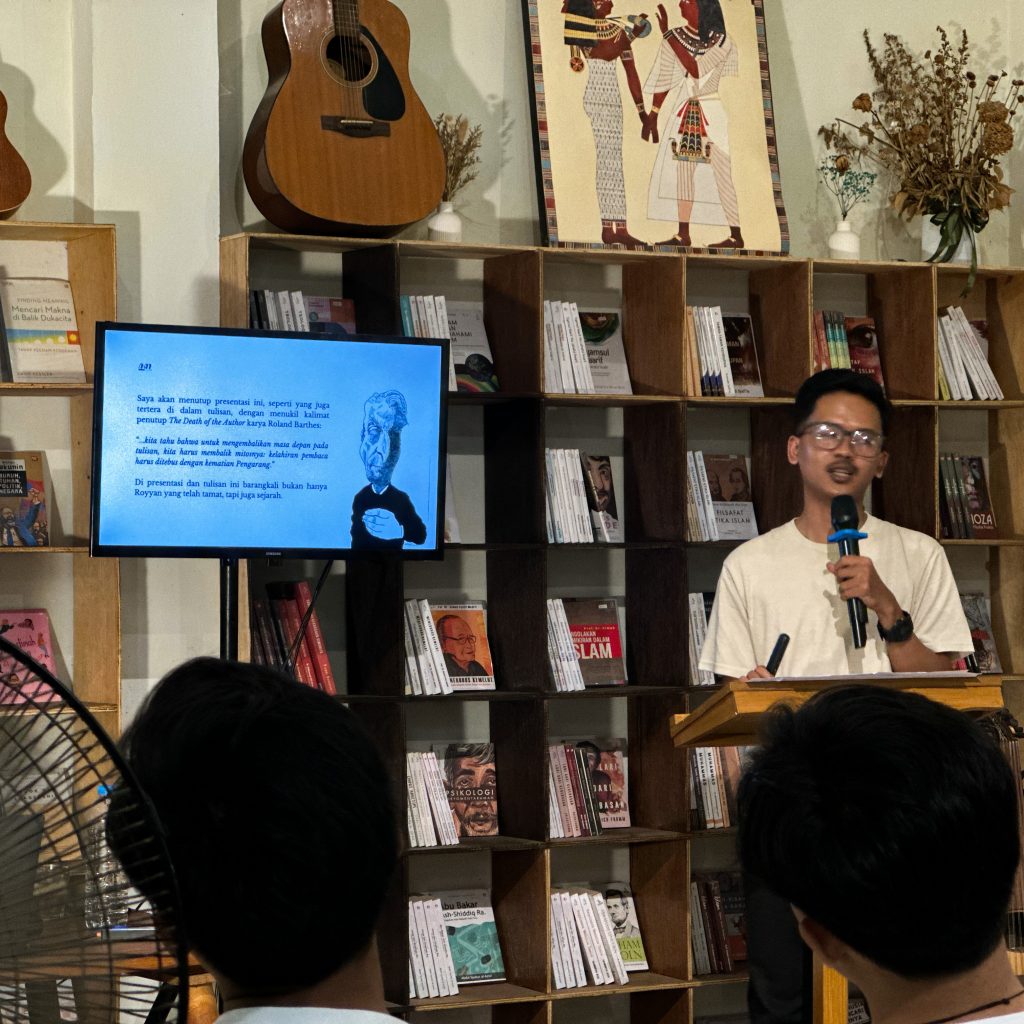
Ia menunjukkan bagaimana siasat Penggunaan personifikasi (misalnya, “ular menggigit ekor waktu”, “bumi dibuhul sembilan bintang”) dan onomatopoeia (suara kuda berlari “ketepak, ketepak”) adalah contoh siasat literer yang digunakan untuk membangkitkan citra dan suasana, bukan sekadar menyampaikan informasi lugas. Ini adalah ciri khas puisi modern yang menjauh dari komunikasi langsung bahasa sehari-hari.
Dia juga mengungkap, Royyan menggunakan sejarah Madura sebagai latar, tapi tidak memfiksasinya sebagai entitas yang tunggal dan mutlak. Sejarah menjadi “remang-remang,” samar, dan terbuka terhadap berbagai tafsir, memungkinkan pembaca untuk mengintervensi dan memperkaya maknanya. Dia berkata “penyair menulis ‘bumi dibuhul sembilan bintang’, ini bukan sekadar citraan visual untuk keindahan. Ini adalah kunci,” papar Ririd. “Sembilan bintang di sini adalah penanda yang sangat jelas, merujuk pada lambang NU. Dalam satu baris pendek, puisi ini berhasil mengikatkan sosok Syekh Kholil pada sebuah warisan historis dan spiritual yang mahabesar, yang masih terasa hingga hari ini.” Tiba-tiba saja penonton tertawa mendengarnya.

Gagasan utama tentang “kematian sejarah” menjadi titik krusial dalam diskusi. Ia ditanggapi oleh beberapa pertanyaan dari penonton, seperti Oci, ibu Dewi, Mas Fani, Kiai Faizi, dan Affan. Ririd menegaskan bahwa ini bukan berarti sejarah telah berakhir, melainkan paradigma sejarah sebagai satu-satunya kebenaran tunggal sudah mati. Sejarah kini dipandang sebagai sesuatu yang cair, elastis, dan dapat terus-menerus ditafsir ulang. Setiap tafsir baru, menurutnya, adalah “sejarah yang lain” yang ikut memperkaya pemahaman kita.
Diskusi yang padat dan filosofis ini ternyata berhasil menjangkau berbagai kalangan pengunjung, termasuk salah satunya adalah Alfian dari komunitas Compok Literasi, yang memberikan tanggapannya. “Acaranya over all bagus. Saya sebagai orang yang awam tentang sastra merasa mendapatkan insight baru, ternyata semendalam itu juga ya puisi yang ditulis. Apa ya, keren pokoknya,” ujar Alfian. Acara bincang buku ini sekali lagi membuktikan bahwa tema-tema sastra yang kompleks dapat dinikmati dan memantik percakapan hangat di ruang publik.
Sastra, Maut, Cinta
Pamekasan diguyur hujan sore itu pada hari Sabtu, 20 September 2025. Tiap tetes air yang jatuh seolah sambutan atas kedatangan dua tamu hebat dari Malang dan Jakarta, Prof. Djoko Saryono dan dr. Sasti Gotama. Sebuah kehormatan besar untuk Sivitas Kothèka, Studium Generale yang diisi oleh dua pemateri sekaligus. Kuliah Umum ini merupakan Koloman Budaya ke-104 yang berjudul “Sastra, Maut, dan Cinta” dibahas tuntas dari berbagai aspek oleh kedua pemateri. Para penonton mendengarkan dengan khidmat, seolah setiap kata yang disampaikan kedua pembicara begitu penting.
Di tengah suasana kafe Balada yang hangat, sastrawan Madura sekaligus dosen Universitas Madura, Royyan Julian, memandu jalannya diskusi yang menyelami kedalaman tema “Epistemologi Maut dan Cinta”. Cahaya lampu yang redup dan rak-rak buku yang menjulang tinggi menjadi latar sempurna bagi perbincangan tentang dua entitas fundamental yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia: Eros dan Thanatos.

Dalam sesinya, Sasti Gotama memukau hadirin dengan presentasinya bertajuk “Anastomosis Maut dan Cinta”, menyoroti betapa kematian adalah pintu masuk universal menuju perenungan eksistensial dalam karya sastra. Ia memaparkan bahwa kematian hadir dalam berbagai wujud, tidak hanya secara fisik, melainkan juga “kematian eksistensial”—seperti mati secara sosial, penolakan dorongan kehidupan, atau pilihan ketiadaan eksistensi. “Banyak maut dalam karya sastra,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa fenomena ini selalu menjadi refleksi terdalam umat manusia.
Merujuk pada gagasan Freud tentang Eros (insting kehidupan) dan Thanatos (insting kematian), Sasti menjelaskan bagaimana keduanya bekerja. Eros, misalnya, termanifestasi dalam insting pelestarian diri—seperti konsep “keegoisan gen” Richard Dawkins—dan upaya memperluas kehidupan melalui jejaring atau karya tulis. Sementara Thanatos, yang mereduksi kondisi hidup menjadi tak hidup, terlihat dalam agresi, pengulangan trauma, atau keinginan untuk kembali ke kondisi anorganik.

Secara mengejutkan, sang dokter juga menunjukkan bahwa Thanatos justru acap hadir demi Eros. Ia memberi contoh pada tingkat seluler: apoptosis atau kematian sel terprogram, yang esensial untuk pembentukan organ (misalnya, jari saat menjadi janin), serta mekanisme perbaikan DNA otomatis yang merupakan ekspresi Eros pada tubuh. “Untuk terus hidup, kita butuh maut,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa sains memiliki bukti empiris untuk paradoks ini. Bahkan, ia menyebut bahwa neurotransmitter (pembawa pesan kimiawi yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi) seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin, yang kerap diidentikkan dengan cinta, juga memiliki jejak Thanatos di dalamnya.

Melengkapi pandangan tersebut, Prof. Djoko Saryono membawa diskusi ke ranah yang lebih filosofis dan kultural, menegaskan bahwa cinta dan maut adalah dua kekuatan purba yang berada di luar kendali manusia. Menurutnya, manusia tidak pernah benar-benar berdaulat atas keduanya. “Kita tidak bisa memilih kapan kita jatuh cinta, kepada siapa kita jatuh cinta, dan bagaimana kita jatuh cinta. Begitu pula dengan maut, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita akan dijemput olehnya,” jelas dia dengan penuh penekanan. Baginya, cinta dan maut adalah misteri agung yang sepenuhnya merupakan takdir, sebuah anugerah sekaligus kutukan yang menentukan jalan hidup manusia.
Oleh karena ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi dua kekuatan dahsyat tersebut, sastra pun lahir sebagai medium untuk memahami dan memaknainya. Sang profesor menguraikan bahwa sejak zaman kuno, sastra menjadi ruang bagi manusia untuk bergulat dengan misteri Eros dan Thanatos. “Karena kita tidak mampu mengendalikannya, maka kita membicarakannya. Kita mencipta cerita, mitos, epos, dan berbagai karya sastra sebagai upaya menafsir dan berdamai dengan takdir cinta dan maut,” ujarnya. Dengan demikian, sastra tidak hanya menjadi cerminan kehidupan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan manusia untuk menyentuh, merenungkan, dan akhirnya menerima dua entitas paling fundamental dalam eksistensinya.
Biografi Persalinan
Acara berikutnya dari gelaran Festival Sastra Sains “Epistemologi Maut dan Cinta” berpindah ke Selasar Al-Kautsar, Serambi Masjid Miftahus Sudur. Halaman Pondok Pesantren Al-Kautsar di Lawangan Daya, menjadi saksi Koloman Budaya ke-105 dengan pergelaran “Monolog Biografi Persalinan”. Acara ini berlangsung khidmat pada Selasa, 23 September 2025 dari pukul 19:30 hingga 22:00 WIB, dipandu oleh Affan Rahmatullah.
Malam dibuka dengan prolog dari Novi Kamalia, Pembina Sivitas Kothèka. Dengan gayanya yang lugas, Novi merajut kisah personalnya tentang cinta dan pengetahuan. Ia bercerita bagaimana pengalaman less memory syndrome atau Alzheimer dini di masa kuliah membawanya pada nasihat seorang profesor: “Jatuh cintalah!” Dari pencarian itu, ia menyadari bahwa cinta merupakan sebuah energi fundamental, bahkan dalam relasinya dengan Tuhan. “Cinta itu adalah sebuah energi di mana kita sudah enggak mau apa-apa,” tuturnya, merefleksikan momen spiritual di depan Kakbah. Novi juga menegaskan bahwa rasa sakit dan cinta, seperti halnya persalinan, bersifat sangat personal. “Kesakitan itu sama tapi rasanya tidak pernah sama,” ucapnya, memberi pengantar yang sempurna untuk tema monolog malam itu.

Pertunjukan monolog “Biografi Persalinan” dipersembahkan oleh Ma’rifatul Lathifah. Wanita yang akrab disapa Mia atau Ma’ Drama itu merupakan seorang sutradara, aktor, dan seniman interdisipliner asal Bangkalan. Ia menampilkan karya tugas akhir magisternya dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang mengulik perawatan raga perempuan sebelum, sedang, dan setelah melahirkan. Di panggung yang bersahaja, Mia menghadirkan berbagai artefak dan gestur yang sarat makna. Ia menjelaskan tentang “abengkong”, seutas kain panjang yang melilit pinggang ibu usai melahirkan—sebuah praktik yang tidak disarankan untuk persalinan caesar. Kursi malas atau kursi goyang menjadi simbol tempat ibu beristirahat selama empat puluh hari pascapersalinan, sebuah periode krusial untuk pemulihan dan mencegah kesemutan atau gangguan kesehatan lainnya.

Mia juga membawa berbagai alat tradisional untuk meracik jamu, seperti gunting khusus rimpang dan wadah penyimpanannya. Ia menyebutkan beberapa bahan jamu Madura seperti kunyit, kayu manis, kapulaga, daun jeruk, dan kulit jeruk nipis. Telur, khususnya telur ayam kampung, yang dicampur minyak kelapa (kelapa biasa, bukan sawit) menjadi ramuan penambah tenaga bagi ibu yang hendak bersalin. “Beberapa bidan pun bilang amis Mbak enggak usah pakai jamu,” kata Mia, mengakui adanya perbedaan pandangan antara medis modern dan tradisional. Namun ia tetap menghargai pilihan masing-masing orang. Pertunjukan ini tidak hanya estetis, tapi juga sebuah upaya untuk membuka percakapan tentang hal-hal yang sering dianggap tabu, termasuk istilah-istilah anatomi perempuan dalam budaya Madura, dan keberanian perempuan untuk menyingkap realitas tubuh mereka.

Setelah pertunjukan yang menggugah, sarasehan dipandu oleh Royyan Julian. Diskusi menjadi semakin kaya ketika salah seorang dari penonton bernama Iqbal berbagi pengalamannya. Ia menceritakan bagaimana penelitiannya dulu tentang jamu Madura untuk tugas kuliah membawanya pada seorang perajin jamu rumahan di Sumenep, Ibu Rukhaniah. Iqbal menemukan bahwa jamu tradisional tidak diproduksi massal dengan takaran standar seperti pabrik, melainkan disesuaikan secara personal. “Mas sampean alergi ini apa tidak, sampean kalau mengunyah ini muntah atau tidak?” tanya Iqbal menirukan Ibu Rukhaniah, yang selalu menyesuaikan dosis berdasarkan kondisi setiap pasien. Hal ini menegaskan adanya “cinta” dan perhatian mendalam dalam proses tradisional tersebut, yang secara langsung memengaruhi efektivitas jamu.
Malam itu, “Monolog Biografi Persalinan” bukan hanya sebuah pertunjukan seni, melainkan juga sebuah jembatan antara sastra, sains, dan kearifan lokal. Ia mengajak audiens untuk merenungkan bahwa proses mulai dari sebelum-ketika-setelah melahirkan merupakan persenyawaan antara maut dan cinta, yang terukir dalam setiap detail tradisi dan pengalaman tubuh perempuan.
Himne kepada Sang Sukma
Puluhan orang memenuhi halaman Pesantren Al-Kautsar pada Sabtu malam, 27 September 2025, menyaksikan sebuah perhelatan magis yang melampaui sekadar konser musik. Di “Selasar Al-Kautsar”, grup musik La Ngetnik asal Sumenep mempersembahkan “Himne Kepada Sang Sukma”, sebuah pertunjukan broadway musik puisi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Festival Sastra Sains “Epistemologi Maut dan Cinta”. Dipandu oleh Zainal A Hanafi dan Adek Agustian, acara yang berlangsung dari pukul delapan hingga sepuluh malam ini mengubah halaman pesantren menjadi ruang ritual yang khusyuk dan energik, dengan alunan musik eksperimental avant-folk yang menggema di bawah langit Pamekasan.
Dibuka oleh Ketua Sivitas Kothèka, Afnan Rahmaturrahman, malam itu didedikasikan sebagai persaksian akan kekuatan bunyi. Ia bersyukur acara yang “agak nakal tapi cerdas” ini mendapat restu penuh dari kedua orang tuanya. “Sejak itulah musik tidak hanya hiburan, tapi juga peringatan akan kefanaan dan pengakuan bahwa cinta tak pernah musnah bahkan ketika maut menutup mata,” ujar Afnan dalam prolognya, menggarisbawahi tema besar festival.
La Ngetnik, yang terdiri dari Rifan Khoridi (Key, Synth, Vokal), Faris Nofail (Gitar), Ruang Harnonis (Vokal), Johariyadi (Perkusi), dan Oding Classic (Bass), membawakan tiga belas komposisi dari album perdana mereka, Lawh (2024). Nama album ini, menurut Rifan, diambil dari serapan kata Lauhul Mahfudz, yang merefleksikan keyakinan bahwa kehidupan adalah peran yang telah tertulis.

Pertunjukan dibuka dengan “Ritus Cermin Semesta”, sebuah lagu yang lahir dari kontemplasi dan kegalauan saat proses pembuatan album, diikuti “Mausimul Hubb”. Selanjutnya, mereka membawakan “Sanasren”, lagu yang diadaptasi dari puisi Alfizin Sanasren. Menurut Rifan, ini adalah sebuah mantra pengasihan. “Ini adalah mantra pengasihan, kata orang Madura, Budul,” ungkapnya.

Setiap lagu adalah narasi. “Barkun” menjadi ekspresi kontemplasi tentang Isra Mi’raj, sementara “Pada Gemawan” menjadi cara mereka titip rasa kepada orang-orang terkasih. Berturut-turut, penonton diajak menyelami “Kisah-kisah”, “Bestari”—sebuah lagu yang paling selaras dengan tema maut dan cinta—dan “Serdadu Ibu”, sebuah ode untuk para ibu. Suasana menjadi lebih reflektif saat “Jawaban adalah Cahaya”, yang liriknya ditulis oleh sang gitaris Faris Nofail, mengalun syahdu.
Kisah di balik lagu “Mistik yang Asyik” juga tak kalah menarik. Liriknya terinspirasi oleh seorang salik bernama Junaid di kampung mereka. “Dia mencintai sesuatu yang tidak ada bagi mata kami, inilah mistik yang asik,” jelas Rifan. Setelahnya, “Askara dan Darma Kelanadibawakan” sebelum pertunjukan ditutup dengan “Rasol”, sebuah lagu cinta romantis untuk Nabi Muhammad. Malam itu, La Ngetnik berhasil membuktikan bahwa musik bisa menjadi jembatan antara yang sakral dan profan, menyajikan sebuah himne yang akan lama bersemayam di sukma para pendengarnya.
Sastra, Spiritualitas, dan Demokrasi
Minggu malam, 28 September 2025, langit Pamekasan yang dingin tidak menyurutkan semangat puluhan hadirin yang memadati Selasar Al-Kautsar. Serambi Masjid Miftahus Sudur di Pondok Pesantren Al-Kautsar menjadi panggung bagi gelaran terakhir Festival Sastra Sains 2025 yang akan ditutup dengan Koloman Budaya ke-107 bertajuk “Sastra, Spiritualitas, dan Demokrasi”. Diskusi kali ini akan dipandu Asief Abdi.
Sebelum diskusi dimulai, Nissa Rengganis, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, menyampaikan sambutan hangat. Penulis Manuskrip Sepi sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon tersebut mengapresiasi Festival Sastra Sains yang ia nilai “menarik dan juga panjang”, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan komunitas sastra. “Kami percaya komunitas sastra itu menjadi pilar penting yang mampu memberikan daya kokoh bagi keberlangsungan kebudayaan,” ujarnya. Ia menambahkan keyakinannya bahwa Pamekasan kelak akan melahirkan novelis, cerpenis, dan penyair sanggup tembus ke level nasional.
Diskusi malam itu menghadirkan sastrawan kenamaan Indonesia, Ayu Utami, penerima berbagai penghargaan seperti Dewan Kesenian Jakarta Award dan Prince Claus Award, yang dikenal dengan novel monumentalnya Saman dan Bilangan Fu. Ayu Utami memulai diskusi awalnya dari suatu hal yang menarik walau tak penting: hantu.
Menurutnya, hantu selalu hadir bersama kesedihan, pesan kehilangan, dan hal-hal yang belum selesai. Ia mengaitkan “hantu-hantu” ini dengan “sejarah gelap Indonesia” yang belum terangkat ke permukaan, seperti korban peristiwa 1965. “Korban-korban itu statusnya bagi sejarah Indonesia itu masih serupa hantu,” tegasnya.

Diskusi menjadi hidup dengan banyaknya penonton yang berbagi cerita. Salah satunya datang dari Ibna, seorang santri yang berbagi pengalamannya di pesantren delapan tahun lalu. “Mbak Mbak… mau pinjam gayung kepala aja enggak punya apalagi gayung,” cerita Ibna menirukan suara hantu di kamar mandi pesantren yang meminta gayung namun mengaku tak punya kepala. Cerita-cerita yang beredar menegaskan pandangan Ayu Utami bahwa hantu bukan sekadar klenik, melainkan sebuah refleksi budaya dan sosial.
Ayu Utami juga membedakan antara “irasional” dan “nonrasional”. Menurutnya, “nonrasional” mencakup hal-hal seperti cinta, musik, atau imajinasi yang tak rasional tetapi tidak buruk. “Padahal kan ada juga yang tidak rasional tapi enggak jelek. Cinta, misalnnya. Cinta, kan, enggak rasional tapi kan enggak jelek,” jelasnya. Sementara itu, “irasional” merupakan nonrasionalitas yang berkonotasi negatif dan perlu dikendalikan. Dalam pandangannya, seni adalah wahana untuk menampilkan kejujuran, bahkan kejujuran yang sulit diterima, melalui cara yang bisa terlihat oleh pembaca tanpa harus menjadi indah.

Gagasan ini resonansinya terasa kuat di benak penonton, salah satunya Ubaidillah dari Tambelangan. Baginya, diskusi malam itu menjadi momen pencerahan. “Dari diskusi sastra ini, Ayu Utami menegaskan bahwa sastra baginya bukanlah sekadar merangkai kata-kata indah. Sastra adalah “pisau bedah” untuk membongkar mitos, narasi besar, dan tabu yang sering kali diterima begitu saja oleh masyarakat,” ungkap Ubaidillah. “Diskusi semalam menyadarkan kita bahwa isu seksualitas, spiritualitas, dan demokrasi yang ia usung dalam Saman dan Larung bukanlah tema-tema terpisah, melainkan satu kesatuan yang berkelindan dalam arena bernama tubuh. Jadi, koloman budaya kali ini penting sekali dan menjadi wajib untuk menghadirinya demi kehidupan literasi,” imbuhnya. Pengalaman malam itu begitu membekas hingga memotivasinya untuk mendirikan komunitas literasi di kampung halamannya.
Malam pamungkas ini menjadi pengingat bahwa sastra memiliki peran krusial dalam menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan spiritual yang kompleks. Ia mengajak untuk tidak takut menggali potensi cerita dari masyarakat, bahkan yang dianggap tabu, dan memanfaatkannya untuk pemaknaan yang lebih baik.
Festival Sastra Sains “Epistemologi Maut dan Cinta” tahun 2025 berhasil menghadirkan berbagai perspektif baru, menjalin silaturahmi, dan menstimulasi kesadaran kolektif tentang irisan takdir manusia, dari panggung kebudayaan hingga relung spiritualitas.
Editor: Asief Abdi
Foto: Mahrus Shofi dan Ahmad Naufal Amini














