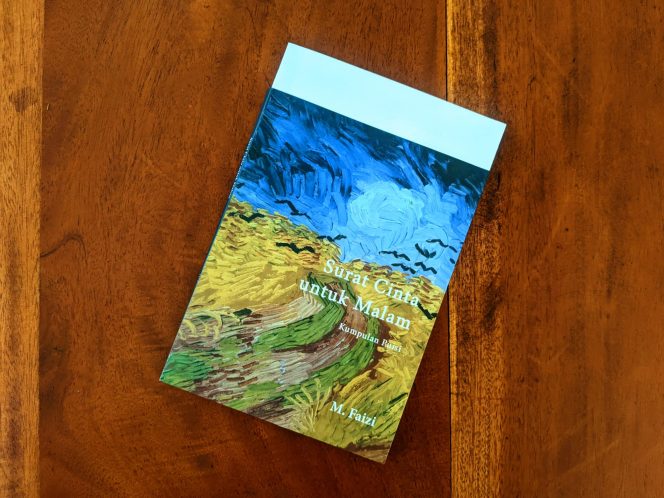Memandang langit malam membentang lapang bertatahkan bintang-bintang, barangkali adalah pengalaman purba sekaligus selalu baru. Di sanalah puisi dan astronomi bertemu. Yang satu menggubah bintang menjadi kata, yang lain menghitung cahaya dalam almanak. Tapi di antara keduanya itu, ada sebuah jarak: kehampaan yang dipenuhi pertanyaan. Dan di sanalah M. Faizi—selanjutnya, dengan tanpa mengurangi takzim, saya sebut Faizi—melantunkan “Himne untuk Malam”.
***
Alam semesta senantiasa mencawiskan tapis-tapis misteri. Setiap kali satu tapis itu tersingkap, kejutan pun menyeruak, bagaikan kelopak bunga yang terburai oleh angin tak terlihat. Si manusia pun gugup. Namun, serentak dengan itu: takjub! Gugup dan takjub, atau yang dalam ungkapan Rudolf Otto disebutnya dengan tremendum et fascinans itu, adalah sepasang perasaan yang acap menjadi akar dari spiritualitas. Barangkali, dari sanalah agama pertama-tama lahir: dari satu malam yang sunyi, di bawah kubah langit bertatah bintang, dan dari seorang manusia yang tak tahu kepada siapa ia harus bicara, kecuali kepada cahaya di nun jauh itu.
Sejak awal peradabannya—bahkan mungkin jauh sebelum peradaban itu sendiri—manusia senantisa memandang langit malam, dengan rasa keingintahuan yang tak terbendung. Berkurun-kurun yang lalu, bintang-bintang adalah kawan bagi para penakluk lautan. Manusia memandang setiap konstelasi bintang-gemintang itu dengan sepasang mata telanjang yang dipenuhi oleh ketakjuban. Adakah itu berarti bintang-bintang, lebih dahulu dikenal manusia ketimbang aksara? Mereka adalah huruf-huruf purba yang dibaca para pelaut untuk mengarahkan sekoci bernavigasi semenjana. Sekali waktu, ia merupa penunjuk jalan, penanda arah pulang. Tapi mungkin juga lebih dari itu, ia adalah isyarat bahwa manusia, bahkan dalam kehampaan lautan, tidak pernah benar-benar sendiri!
Kemudian datang Galileo membawa mata yang baru. Teleskop pertama membuat yang jauh terasa lebih dekat, yang samar menjadi terbilang terang. Sejak itu, manusia makin bernyali mendekatkan mata ke paras langit, bahkan ingin menembus tapis misterinya. Lalu, mereka tak hanya ingin melihat, tapi juga melampaui. Wahana-wahana antariksa pun diciptakan. Voyager dikirim jauh menembus ruang antarplanet. Dan hari ini, Webb membuka kelopak pandang yang bahkan bisa menatap awal mula semesta. Tapi semakin jauh kita menjelajah, semakin terasa bahwa satu-satunya kemegahan yang menyambut di antara sekat galaksi, rupa-rupanya hanyalah gelap dan sunyi, yang perkasa, yang meraja, yang digdaya!
Laut itu, kita menyebutnya kosmos. Dan manusia, untuk pertama kalinya benar-benar sadar bahwa ia bukan penguasa panggung. Ia hanya serpih dari puing-puing bintang mati. Debu—yang berpendar hanya karena cahayanya dipinjam dari sesuatu yang lebih dulu lenyap. Carl Sagan menyebut perjalanan menuju ke angkasa luar sebagai perjalanan pulang menuju ke asal-usul, sebab debu-debu bintang itulah rupa-rupanya yang membentuk jasad wadak kita. Maka, menjelajahi angkasa luar adalah juga upaya menjelajahi diri dengan maksud bukan sekadar untuk mengetahui lebih banyak apa yang sebelumnya urung diketahui, melainkan untuk memahami lebih dalam. Lalu bertanya: siapa sejatinya kita di dalam semesta? Pertanyaan itu, saya bayangkan bergetar, mengguncang dinding-dinding rohani Faizi, ketika ia membuka puisinya dengan:
Aku menyaksikan bintang-bintang di langit,
berdiri tegak, kepala mendanguk
tatapan tajam tapi terasa rabun,
berpijak kaki tapi terasa limbung.
Dibuka dengan adegan visual: “Aku menyaksikan bintang-bintang di langit”, secara tiba-tiba, Faizi segera membelokkan teropong pembacaan dan kesadaran kita. Si aku lirik itu berdiri tegak, tetapi kepala mendanguk, tatap mata yang tajam itu ternyata rabun, dan kaki yang berpijak pun rupanya limbung. Kita dihantam oleh konfrontasi sejak bait pertama. Seolah-olah, pertentangan-pertentangan itu mengisyaratkan sebuah disorientasi eksistensial yang segera saja menyesaki diri si aku lirik. Ketegangan antara yang tampak dan yang tak tertangkap pun mulai terasa. Setelahnya, penyair mempertemukan dua kata kunci, iman dan ragu, yang saling berpagutan.
“Berpagutan”, kata yang dipilih Faizi itu, saya percaya, tak asal dicomot dari kamus diksi berlimpahan di tubuh kepenyairannya. “Berpagutan” menyiratkan adanya tarik-menarik yang tak kunjung usai, saling berebut dominasi, laiknya adegan dua kekasih saling beradu cium. Adakah pandang terhalang embun/atau mataku yang mulai tumpul?// Hamparan-hamparan pertanyaan/memayungi langit malam,” tanya si aku lirik kemudian, dan kita tahu, puisi ini mulai menggeser citraan visualnya menuju senarai pertanyaan epistemologis: Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu?
Mari kita sejenak melesat ke lain persoalan, yang, dalam hal ini, sebetulnya masih mengandung centang-perentang keterkaitan. Carl Sagan, suatu kali pernah menulis bahwa kita semua terbuat dari partikel bintang. Pernyataan Sagan tersebut tentu bukan dalam semangat kepenyairan, tetapi dalam kenyataan kosmologis. Bahwa atom-atom dalam tubuh manusia, adalah residu dari bintang-bintang yang meledak miliaran tahun yang lampau. Maka kita, para pengamat malam, sebenarnya sedang menatap muasal tubuh kita sendiri yang bersinar dari kejauhan itu.
Namun, seperti dalam puisi Faizi, tatapan itu tak cukup. Kita mampu menatap, tetapi tak mampu melihat. Kita membaca bintang seperti “sandi yang sukar dibaca.” Di sinilah puisi bersetubuh dengan fisika—taruhlah begitu, sebab saya bingung pula mencari padanan impresi yang saya tangkap sendiri. Bahwa cahaya bintang yang kita lihat di malam ini, adalah juga masa lalu. Apakah itu berarti, kita sejatinya tak pernah benar-benar melihat langit sebagaimana adanya, melainkan sekadar sebagaimana ia pernah ada? Dalam bait-bait berikutnya, Faizi membawa kita menuju pusat renungannya: keterbatasan manusia dalam menatap semesta dan makna. Ia menulis:
Di antara mata yang menatap namun tak mampu melihat,
jantung berdetak namun tanpa takut dan harap.
Aku membaca larik-larik panjang bentala berhias cahaya
seperti sebuah sandi yang sukar dibaca.
Tertunduk ragu,
di antara batas terjauh kemampuan melihat
dan titik terendah tempat kaki menapak,
memikirkan hidup yang singkat dan tahun cahaya,
antara maut dan supernova,
aku tersedak saat bertanya:
Seberapa lama orang akan mampu mengenang
dan menghargai sebuah karya pemikiran?
Dua bait itu membawa ingatan saya terbang pada larik-larik puisi “Manusia Pertama di Angkasa Luar” karya Subagio Sastrowardoyo, pertanyaan yang disodorkan si aku lirik di atas agaknya tak sekadar bicara soal ingatan, tetapi juga tentang kefanaan intelektual. Di tengah galaksi yang tak memedulikan makna, bisakah pemikiran manusia tugur bertahan? Seberapa lama orang akan mampu mengenang/dan menghargai sebuah karya pemikiran? tukas aku lirik. Namun, struktur puisi Faizi kemudian seperti berpindah arah. Berangkat dari sebentang langit, ia mengajak kita pulang ke palung hati. Dus, penyair barangkali hendak membawa imajinasi kita membayangkan bagaimana guncangan keberadaan aku lirik, yang pada akhirnya diubah dari sebentuk pengamatan menjadi perenungan secara radikal. Walhasil, ia tak lagi hanya seorang yang bertanya, tapi menjelma seorang yang belajar.
Aku lirik menyadari bahwa melihat saja rupanya tak cukup tanpa berpikir. Jika mata melihat namun tanpa berpikir/yang tampak hanyalah gugusan, galaksi, bimasakti, dan berpikir belaka, ternyatalah juga tak lagi berarti tanpa zikir, tanpa mengingat. Apakah gunanya berpikir jika tak berzikir? Apakah gunanya ilmu pengetahuan jika hanya menghitung jumlah dan jarak?” resah si aku lirik, menegaskan sebuah kesadaran yang nyaris metafisik, bahwa pengamatan, perhitungan, bahkan pengetahuan ilmiah sekalipun, tidak menjawab kehampaan batin yang mengguncang telak eksistensi manusia. Kita simak kembali bait-bait Faizi.
Aku menyaksikan bintang-bintang yang berserakan
luas, indah, dan tak terhingga.
Manusia menjangkaunya dengan ilmu pengetahuan
namun langit selalu menjauh di dalam pengertian.
Faizi melanjutkan puisinya dengan kalimat yang seakan membangun pialang antara rasionalisme dan spiritualitas. Manusia menjangkaunya dengan ilmu pengetahuan/namun langit selalu menjauh di dalam pengertian,” tulisnya, dan saya lantas tercenung. Dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, manusia dapat mengukur jarak antargalaksi, tapi ia tak bisa mengukur makna keberadaan diri di dalamnya. Langit, yang berupaya digapai dengan ilmu pengetahuan, justru “selalu menjauh di dalam pengertian”. Kita bisa merumuskan hukum-hukum gravitasi, tetapi toh kita tetap tertunduk—sebagaimana ditulis Faizi—di antara maut dan supernova. Ada juga sejenis renungan teologis; sebuah tafakur tentang penciptaan. Faizi menulis:
Sesungguhnya, aku adalah ciptaan yang mahapelupa
karena itu belajar mengingat dengan cara memberi nama.
Sedangkan Pencipta senantiasa menegur
agar di saat berdiri, duduk, dan berbaring hati bergetar
tak pernah tidur, tak pernah tidur, tak pernah tidur.
Hanya ketika jagalah aku harus berpikir,
namun setiap detak jantung iring-seiring berzikir.
29/09/2017
Pada bait di atas, kita saksikan bagaimana penyair menggambarkan si aku-lirik mengaku sebagai makhluk “mahapelupa”. Dan karena itulah, ia mesti belajar mengingat dengan cara memberi nama. Maha Pelupa; frasa ini mengingatkan saya tentang satu istilah dalam ilmu nahwu, yakni isim tafdhil atau juga jamak disebut sebagai af’alut tafdhil. Barangkali saya perlu menyinggungnya sepintas.
Sesuai dengan maknanya yang mengandung unsur perbandingan, ism tafdhil tergolong sebagai kata benda (isim) dan mengikuti pola أَفْعَلُ (af‘alu). Isim ini terbentuk dari kata sifat dengan mengambil akar katanya terlebih dahulu, lalu dibentuk mengikuti pola tersebut. Secara bentuk, ism tafdhil memang menyerupai fi’il karena memakai pola yang juga dikenal dalam bentuk kalimat kerja. Namun, meski secara gramatikal ia adalah isim, fungsinya adalah untuk membandingkan dua hal dan menunjukkan bahwa salah satunya memiliki kelebihan dibanding yang lain. Dalam struktur kalimat, jenis kata ini digunakan untuk mengungkapkan makna superlatif (paling/ter-) atau komparatif (lebih dari).
“Mahapelupa” pada bait di atas ialah semacam pengakuan eksistensial bahwa manusia, tidak hanya “pelupa”. Lebih dari itu, ia adalah “makhluk yang paling pelupa”. Nyatanya memang manusia tidak hanya lupa pada hal-hal kecil, tetapi juga acapkali lupa bahkan pada hal yang paling hakiki. Ia mudah lupa dengan sangkan-parannya, asal-usulnya, makna keberadaannya, bahkan pada Pencipta yang menciptakannya. “Mahapelupa” ialah bentuk ungkapan superlatif. Ia mirip fungsi isim tafdhil dalam bahasa Arab yang—sebagaimana sudah disinggung—digunakan untuk menandai “yang paling …” atau “lebih dibanding yang lain”. Dalam bahasa Arab, isim tafdhil dibentuk dari kata sifat, lalu diberi pola أَفْعَلُ (af‘alu). Misalnya saja, منسيّ (mansiyy) yang berarti “yang dilupakan”, begitu mengikuti wazan (pola) tafdhil-nya, ia bisa menjadi أَنْسَى (ansā) yang berarti, “paling terlupa” atau “yang maha pelupa”.
Dus, “mahapelupa” secara fungsi semantik sejajar dengan struktur isim tafdhil. Ia bukan hanya kata sifat, tapi sebuah pengakuan superlatif sekaligus komparatif yang menyatakan bahwa manusia—dibanding ciptaan lainnya—tidak saja lebih pelupa, bahkan mungkin yang maha pelupa. Tapi Faizi, kita melihat, tidak berhenti cukup sampai di situ. Ia mengarihkan semacam kelokan semantik: justru karena manusia adalah makhluk mahapelupa, manusia belajar mengingat melalui nama-nama. Dalam kerangka pemikiran Qur’ani—misalnya, tentang pengajaran nama-nama kepada Adam—menamai adalah tindakan mengenang, mengenali, sekaligus memahami. Maka dalam kekurangannya itulah, manusia justru diberi potensi kelebihan, yakni melawan lupa dengan nama, dengan bahasa.
Dari sini, kemudian kita akan menyaksikan sebuah ambivalensi. Manusia—yang paling pelupa itu—pada saat yang sama, jugalah makhluk yang paling mampu mengingat. “Mahapelupa” dalam larik Faizi, dengan demikian, menjadi cermin keterbatasan di satu sisi, tetapi juga keistimewaan di sisi yang lain: manusia itu ansā, maha pelupa, tetapi serentak dengan itu, yang juga paling dicatat. Tapi dengan apakah manusia menjadi yang paling dicatat? Faizi menunjukkan, yakni dengan teguran. Terhadap makhluk yang mahapelupa itu, Tuhan digambarkan penyair sebagai Pencipta yang “senantiasa menegur”. Teguran itu—berbeda dengan teguran dalam sinetron-sinetron azab di mana misalnya, jenazah seorang penyabung ayam dipatuki sepasukan pitik misterius sebagai pengingat bagi umat yang lalai—berupa detak hati yang bergetar; kewaspadaan yang tak pernah tidur. Bahkan ketika jasad manusia diam, batin mesti tetap menyala. Sedangkan Pencipta senantiasa menegur/agar di saat berdiri, duduk, dan berbaring hati bergetar/tak pernah tidur, tak pernah tidur, tak pernah tidur/
“Bagaimana manusia berdiri di bawah langit yang maha luas? Mampukah ia melihat, mengerti, dan mengingat? Carl Sagan, dalam Pale Blue Dot, menatap bumi dari jarak 6,4 miliar kilometer dan menyebutnya “a mote of dust suspended in a sunbeam.” Sebuah titik debu yang mengambang dalam cahaya. Begitu kecil. Begitu rentan. Amatlah rapuh. Tapi di situ, di titik debu yang mengambang dalam cahaya itu, seluruh sejarah manusia berlangsung: cinta, perang, filsafat, puisi. Segala macam! Apakah Faizi bermaksud menempatkan manusia dalam skala semesta, lalu mempertanyakan bobot keberadaannya? Sebagaimana ia tulis dalam himnenya? Apa makna berpikir jika tak disertai kesadaran akan keterbatasan? Apa gunanya puisi, atau bahkan sains, jika tak membawa kita pada zikir, pada rasa gentar terhadap kesadaran akan keberadaan?
Saya sebetulnya tak mengerti, dan karena itulah saya bertanya-tanya, mengapa secara formal, puisi ini terasa menghindar dari bentuk yang terlalu padat? Padahal, saya secara pribadi membayangkan, dalam bentuk yang padat, puisi ini barangkali akan begitu menjadi bertenaga. Larik-larik seperti “Sesungguhnya, aku adalah ciptaan yang mahapelupa/ karena itu belajar mengingat dengan cara memberi nama” hemat saya, akan lebih cantik begitu ditulis lebih ringkas menjadi, misalnya: “Aku ciptaan yang mahapelupa/ karenanya belajar mengingat dengan memberi nama”. Namun, segera saja tajuk puisi ini menyergah angan-angan saya. Ia mengingatkan bahwa apa yang ditulis penyair adalah sebuah himne, bahkan dalam artinya yang paling literal, yakni nyanyian malam untuk yang tak terkatakan. Tapi mungkin puisi ini adalah juga zikir itu sendiri. Oleh sebab itu, ia mungkin memang tak ingin tergesa-gesa dalam menyampaikan makna. Dan tidakkah repetisi seperti “tak pernah tidur, tak pernah tidur, tak pernah tidur” memanglah menyerupai bentuk zikir itu sendiri—sebuah getaran ritmis yang menandai kesadaran batin?
Betapa pun saya telah coba mengait-hubungkan pembacaan saya dengan astronomi, saya sejatinya insyaf bahwa Faizi, dalam himnenya, sepertinya tidak sedang menjelaskan langit. Ia sedang berdialog dengannya. Ia menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai cara untuk mendekat alih-alih memahami. Mungkinkah si penyair bermaksud untuk menegaskan bahwa pemahaman pada akhirnya tidak pernah jangkap? Bahwa pemahaman bukanlah ujung dari pencarian, tetapi justru keheningan yang memeluk ketakmengertian? Saya tak tahu. Jawaban itu, biarlah dia jawab di atas bangku Kafe Pustaka yang memar nanti.
***
Malam, kita tahu, adalah saat di mana langit terbuka, sekaligus saat ketika kesendirian dan kesunyian menjadi terasa begitu digdaya. Dalam dunia yang telah kebak oleh angka dan aksioma ini, “Himne untuk Malam” seakan-akan hendak mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat diukur, dapat diskalakan, sebagaimana halnya tak semua cahaya bisa dipahami sebagai panjang gelombang. Ada saat-saat di mana cahaya itu adalah “sesuatu”, adalah metafora untuk mengungkapkan bagaimana “sesuatu” yang tak dapat direduksi oleh bahasa itu datang menyesaki dada, tapi tak pernah kuasa terukur oleh, katakanlah, spektrometer. Bolehkah kita menyebutnya cahaya iman?
Ketika Faizi kemudian menutup puisinya dengan sebaris titimangsa “29/09/2017”, saya bayangkan ia mengabadikan malam saat puisi itu pungkas dianggitnya. Dan dengan cara itu, ia menandai bahwa malam dalam puisinya adalah malam yang sebetulnya terus terjadi. Ia adalah malam dalam diri setiap manusia yang memandang bintang, lalu mendapati dirinya kecil, rapuh, dan disesaki beragam tanda tanya. Saya ingat, dalam The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Sagan suatu kali berkata, “Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality.” Sains, demikian kata Sagan, tidak hanya cocok dengan spiritualitas; sains merupakan sumber spiritualitas yang mendalam. Faizi, dalam puisinya pun, saya kira menegaskan hal yang kurang lebih serupa dengan Sagan. Di batas antara bintang dan doa, di tubir antara taksir dan zikir, manusia berdiri di tengah-tengahnya. Ia mendongak, tetapi kemudian tertunduk ragu. Dan dalam setiap detak jantung yang iring-seiring berzikir itu, ia mengingatkan kita seluruhnya: berpikir dan beriman barangkali tidak selalu bertentangan. Keduanya, mungkin hanyalah dua sisi dari paras malam yang sama.
Yohan Fikri adalah penyair dan kritikus sastra.
Editor: Ikrar Izzul Haq