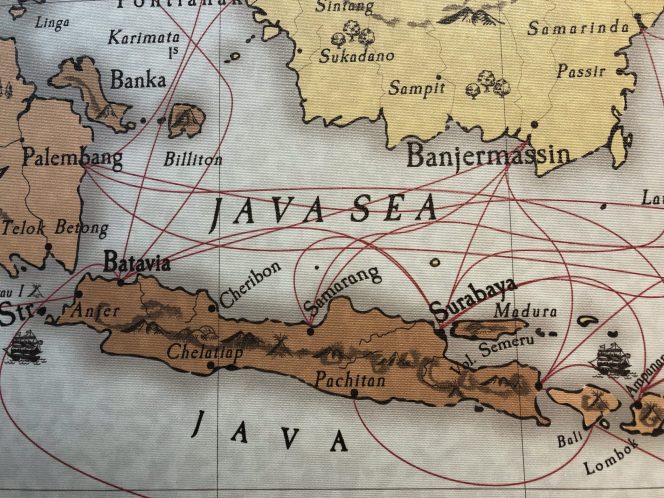Diponegoro mengemban gelar Erucakra alias “Ratu Adil” di Tanah Jawa—seperti diimajinasikannya sendiri dalam babad yang ia tulis. Sebutan tersebut tak lepas dari kehebataannya dalam memberontak serta kegandrungannya pada perihal mistik. Dia, menurut Peter Carey, menyetarakan diri dengan Arjuna. Ke-fomo-an sang pangeran tercermin dari penamaan wangsit berupa anak panah yang diberikan Sunan Kalijaga yang diubah menjadi belati oleh Diponegoro. Belati itu ia namai “saratama” (senjata yang dipakai Arjuna dalam Perang Mahabarata). Pemilihan tokoh pandawa tersebut mengisyaratkan Diponegoro sebagai sosok berwibawa sekaligus sang pembebas.
Carey mencatat kalau konsep Erucakra yang dimaksud Diponegoro yaitu penguasa yang adil serta wali mudhar yang berarti “wali dengan jabatan rangkap sebagai raja sekaligus pemimpin spiritual”. Logika serupa juga pernah diterapkan Airlangga waktu memimpin Kahuripan, ketika ia moksa, menghindari hiruk pikuk duniawi dan naik ke lokus yang lebih tinggi. Bagi Carey, nalar tersebut juga diadopsi Diponegoro lewat pengasingannya ke Sulawesi: wujud moksa demi melegitimasi diri sebagai sang wali. Erucakra, menurut analisis Carey dalam Babad Diponegoro dan Babad Kedung Kebo, dianggap bagian dari upaya Diponegoro memantapkan diri sebagai raja tanpa mahkota yang datang untuk membebaskan dan berkuasa dengan adil kelak.
Dalam babadnya, Diponegoro juga memandang bahwa dirinyalah yang akan mewujudkan ramalan Jayabaya dan menjadi raja yang adil dan lurus. Dalam nubuat tersebut, Jawa bakal dipimpin oleh sang Erucakra yang berdarah wali, yang besar dari keluarga pandita raja dengan kerendahan hati dan sudi berjuang demi kepentingan rakyat. Diponegoro mendapat dukungan kalangan pangeran yg kebanyakan terkenal punya spritualitas tinggi sehingga meyakinkan orang bahwa sosok Erucakra itu adalah dirinya. Dalam Serat Cabalang yang muncul bersamaan dengan masa itu, dikisahkan kalau Erucakra akan kalah saat raja dari Nusa Srenggi (Eropa) tiba.
Konsep semacam itu juga diterapkan oleh Soekarno ketika menyambut Jepang dan juga pada masa-masa pascamerdeka. Julukan Seokarno Ratu Adil, Soekarno Panglima Besar Revolusi, Semboyan Revolusi Soekarno, Anti-Neokolonialisme, dan Perang fii Sabilillah digunakan para pemimpin nasional agar rakyat mau ikut serta mempertahankan kemerdekaan dari kaum penjajah.
Diponegoro, masih dalam babadnya yang ditulis setelah dirinya tinggal di pengasingan, mengungkapkan bahwa sebenarnya ia berencana melakukan serangan terhadap Yogyakarta sebagai wujud protes lantaran keraton tidak menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Menurutnya, dengan latar belakang Islam, Mataram seharusnya menerapkan nilai-nilai agama. Sayangnya, serbuan tersebut terhalang oleh bekingan Belanda.
Sang Pangeran lahir dari seorang selir Sultan Hamengkubuwono III. Dalam tradisi keraton, Diponegoro bukanlah putra mahkota sebab ia lahir dari rahim yang tidak sah secara hukum. Akibatnya, saat terjadi hiruk-pikuk pergantian kuasa dari Hamengkubuwono IV ke V , Diponegoro tidak mampu berbuat banyak sehingga hanya mentok menjadi dewan penasehat kerajaan. Namun, jabatan tersebut malah menjadikan Diponegoro mampu mengawasi dan melakukan kritik terhadap kebijakan Danurejo selaku Pelaksana Harian Sultan HB V yang saat itu masih berusia tiga tahun. Bahkan dari situlah, ia mulai melancarkan serangan untuk mengusir pengaruh Belanda dari kerajaan yang kemudian dikenal Perang Jawa.
Dalam aksinya, Diponegoro menggunakan siasat gerilya dengan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Taktik tempur yang dijalankan oleh pasukan Diponegoro ternyata menyulitkan Belanda dalam menumpas para pemberontak. Maka, pada tahun 1827, Jenderal De Kock menerapkan strategi baru yang dikenal dengan nama Benteng Stelsell atau Siasat Benteng dengan membangun benteng-benteng pertahanan. Untuk menghindari jatuhnya korban yang kian mempersempit ruang gerak, Belanda menggunakan muslihat licik dengan berpura-pura mengajak sang pangeran berunding. Diponegoro yang lengah lantas ditangkap dan diasingkan ke Manado pada 3 Mei 1830.
Perpaduan antara motif agama dan ekonomi menyebabkan pertempuran melawan Diponegoro sangat menyita kas pemerintah kolonial hingga mereka nyaris bangkrut. Korban perang dari pihak Belanda sekitar 15.000 orang (8.000 orang Eropa dan 7.000 orang pribumi). Konflik militer berlarut-larut tersebut menelan 20 juta gulden. Sementara itu pihak Pangeran Diponegoro kehilangan lebih kurang 200.000 orang. Padahal, total penduduk Hindia-Belanda waktu itu baru tujuh juta orang, sedangkan separuh penduduk Yogyakarta terbunuh (Ricklefs, 2008).
Basis kekuatan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi dua kubu besar dari komunitas Islam: kalangan santri dan kiai. Diponegoro sejatinya juga merupakan santri dari beberapa kiai dan ulama, termasuk santri dari Kiai Taftayani yang memberikan pencerahan kepada sang pangeran tentang Islam dan perang melawan kebatilan. Oleh karena itu, dia tentu paham betul karakter seorang santri.
Para santri berperan penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan gagasan, ide, dan seruan kepada masyarakat untuk membantu Diponegoro dalam memerangi kebatilan. Mereka memiliki jaringan yang sangat luas, dari Tegalrejo sampai ke kawasan yang jauh. Dalam tradisi pesantren, terdapat sebuah tradisi yang turun menurun, yaitu semacam pengembaraan ilmu ke suatu daerah yang telah ditentukan atau ke tempat santri tersebut tinggal untuk menyebarkan ajaran Muhammad dan menyalurkan keilmuan mereka atau biasa disebut dakwah. Kondisi tersebut dimanfaatkan sang pangeran untuk membantu mengusir bangsa kolonial. Alasan lain kaum santri ikut berperang di sisi Diponegoro yakni untuk mengembalikan kultur Jawa yang telah dinodai Barat. Selain itu, mereka juga ingin mendukung sang pangeran dalam membangun sebuah negara yang bernapaskan Islam.
Sementara itu, golongan kiai dan ulama juga memainkan peran yang tak kalah krusial. Tak cuma agama, mereka juga mempelajari ilmu tempur (ngelmu kadigdayan), ilmu kesaktian (ngelmu kawedukan), bahkan juga mempelajari ilmu kebal peluru dan senjata tajam (ngelmu keselamatan) (Lutfiyah, 2021). Para kiai pula yang menyerukan bahwasanya melawan dan mengusir penjajah juga merupakan jihad fi sabilillah, yang punya makna berperang melawan orang kafir dan demi menegakkan panji agama.
Selain dari komunitas Islam setempat, kekuatan Diponegoro disokong daerah-daerah lain dengan kekuatan yang berbeda-beda, seperti Madiun, Pajang, Bagelen, dan Mataram. Di samping itu, ia juga mendapatkan pertolongan dari kerabat terdekat dan golongan bangsawan keraton, seperti Pangeran Suryodiningrat, Pangeran Adisuryo, Pangeran Joyowinoto, dan Bupati Mangunnegoro. Pangeran Diponegoro juga memiliki panglima yang cukup kuat, antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ngabehi Joyokusuma, Sentot Alibasa, dan Abdul Mustafa Prawirodirjo.
Dalam menghadapi musuh, Pangeran Diponegoro membagi pasukan ke dalam beberapa bagian yang tersebar di tiap daerah. Lalu, ia menjadikan Gua Selarong sebagai basis kekuatan bala tentaranya. Sang pangeran mengutus telik sandi ke berbagai zona-zona penting. Para laskar disiapkan untuk siaga tempur bila sewaktu-waktu perang pecah. Strategi yang digencarkan oleh Diponegoro yaitu gerilya: melawan musuh secara serentak dalam waktu yang berbeda atau sebaliknya. Lain dari itu, ia juga membuat beberapa pabrik mesiu yang tersebar di beberapa kawasan.
Setelah sempat diasingkan ke Manado, Diponegoro dipindah ke Makassar. Di sana, ia ditempatkan di Benteng Rotterdam, tempat yang sangat luas untuk seukuran pangeran Jawa. Disampaikan juga oleh Baud seorang perwira militer Belanda yang bertugas di sana kalau Diponegoro tidak diperlakukan selayaknya tahanan lain. Tidak seperti gambaran Raden Saleh, sang pangeran mendapat perlakuan khusus bahkan diperbolehkan mengambil alih barak militer Belanda untuk dijadikan tempat tinggal. Diponegoro, tulis Carey, merupakan tahanan negara yang mendapat perlakuan istimewa: anak-anaknya diizinkan untuk menikah dengan penduduk setempat. Ia juga diperkenankan tinggal bersama anak istrinya.
Seabad kemudian, napas gerilya kembali berembus di Tanah Jawa. Strategi tersebut digunakan dalam Pertempuran Surabaya tahun 1945. Saat itu Mayjend Soengkono membagi Surabaya menjadi tiga komando militer di bawah pimpinan Komandan Batalyon. Tiga batalyon itu dibagi lagi menjadi beberapa kompi di setiap kecamatan.
Kompi-kompi tersebut menaungi laskar-laskar rakyat yang ingin bersatu membantu serdadu Indonesia berperang melawan Belanda. Gerilya cukup membuat repot Belanda yang saat itu dibonceng Inggris untuk menegakkan kembali kendali kolonial. Inggris mengalami banyak kekalahan dalam pertempuran tersebut. Tewasnya A.W.S. Mallaby dan prajurit lainnya memaksa pasukan Inggris mundur dari pusat kota.
Taktik gerilya dianggap sebagai “strategi pelelahan lawan” lantaran Belanda terpaksa mencari jalan untuk melakukan kontra-gerilya meski pilihan tersebut menuntut lebih banyak korban dari kalangan personelnya sendiri (Oostindie, 2016). Korban-korban tersebut berjatuhan bukan karena Belanda tidak punya tentara tangguh, melainkan mereka harus berperang di tengah hamparan lahan, hutan, dan berbagai lanskap geografis wilayah Indonesia yang menyulitkan gerak-gerik serdadunya.
Gerilya dan siasat infiltrasi pasukan militer Indonesia dilakukan dengan keunggulan jumlah pasukan. Layaknya Perang Jawa, tentara Indonesia di Surabaya juga dibantu penduduk lokal yang memiliki kesamaan visi. Siasat tersebut di beberapa kesempatan memang bisa membuat Belanda ketar-ketir, tapi tetap saja tak sukses mengusir Belanda dari negeri ini. Keahlian tentara Belanda dan Sekutu memaksa pertempuran yang mereka sebut “upaya dekolonisasi” mesti berakhir di meja runding setelah tentara Republik Indonesia berhasil dipukul mundur. Upaya damai itu sebenarnya tidak menunjukkan kemenangan Belanda, tapi menunda kerugian perang yang berkepanjangan.
Semangat merdeka dan motif agama—dengan menyebut perang kontra Belanda dan Inggris di Surabaya sebagai bentuk perang sabil—makin membakar gelora laskar-laskar simpatisan tentara Indonesia untuk menyerbu Sekutu secara membabi buta. Spirit yang seabad sebelumnya membuat penjajah gelagapan, kembali menyala dari jiwa-jiwa yang haus kemerdekaan.
Senarai Pustaka
Carey, Peter. 2012. Asal Usul Perang Jawa : Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh. Yogyakarta: LkiS.
Carey, Peter. 2017. Sisi Lain Diponegoro : Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Lutfiyah. 2021. Strategi Diponegoro dalam Menggerakkan Semangat Jihad Masyarakat Islam di Jawa. Malang: Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), 1(3), 2021, 368-378.
Oositindie, Gert. 2016. Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Riklef, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-1400. Jakarta: Serambi.
Ainun Novaldi merupakan seorang alumnus pendidikan sejarah.
Editor: Asief Abdi