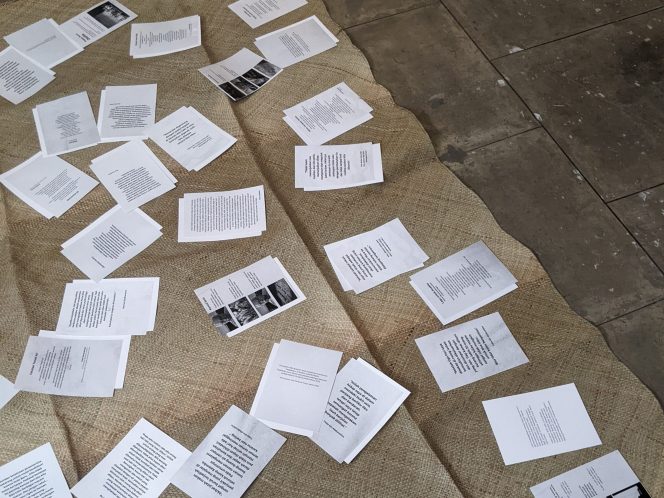Royyan Julian, Dwi Ratih Ramadhany, dan Muna Masyari merupakan tiga penulis asal Madura yang terkemuka. Karya-karya mereka tersebar di berbagai media dan kerap mendapatkan penghargaan. Esai ini merupakan gambaran penelitian tentang representasi perempuan di Madura dalam karya sastra yang ditulis oleh ketiga penulis tersebut. Sebagian besar perempuan Madura yang digambarkan dalam karya sastra adalah perempuan dari keluarga kelas bawah. Mereka rentan mengalami penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat Madura yang patriarkis, tidak hanya dari laki-laki tetapi juga dari perempuan. Selain itu, hidup sebagai perempuan di Madura yang agama dan etnisnya berbeda dengan agama dan etnis dominan juga tidak mudah.
Perempuan dan Budaya Madura
Untuk menganalisis posisi dan peran perempuan di Madura dalam karya sastra, kita tidak mungkin menghilangkan faktor-faktor yang membentuk masyarakat Madura. Karya sastra dari penulis asal Madura menggambarkan tokoh perempuan Madura yang mengalami penindasan dari ekspektasi sosial dan budaya Madura. Perempuan Madura umumnya dianggap sebagai simbol prestise bagi masyarakat, keluarga, dan bahkan pria. Memegang posisi sebagai simbol prestise bagi keluarga dan pria, perempuan Madura secara budaya dituntut untuk mematuhi berbagai aturan kesopanan hingga kebajikan, mulai dari cara berpakaian, berperilaku, berbicara hingga bersosialisasi dengan lawan jenis atau orang yang lebih tua (Mardhatillah, 2014). Dapat disimpulkan, nilai-nilai femininitas perempuan Madura terkait erat dengan konstruksi sosial-budaya. Seperti masyarakat patriarki lainnya, masyarakat Madura cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Akibatnya, perempuan Madura ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.
Cerpen “Rumah Hantaran” karya Muna Masyari (2019) mengungkapkan bagaimana tokoh protagonis, seorang perempuan Madura, diopresi oleh ekspektasi budaya yang dilambangkan oleh rumah sebagai mahar pernikahannya. Ibu dari tokoh protagonis menekankan bahwa semua aspek dalam rumah tersebut menandai pentingnya menjadi perempuan dan istri yang baik serta sesuai dengan norma dan nilai masyarakat di Madura. Tokoh protagonis kemudian merasa tercekik oleh adanya gagasan ideal perempuan Madura yang dipegang teguh oleh masyarakat ketika dia mengetahui bahwa suaminya telah mengkhianatinya dengan berselingkuh. Selanjutnya, tokoh protagonis menyadari bahwa mahar berbentuk rumah dan perangkatnya bukanlah simbol kemakmuran atau kemuliaan perempuan, melainkan simbol kurungan yang memenjarakan perempuan Madura di balik status sebagai seorang istri. Di akhir cerita, tokoh protagonis kemudian mematahkan pilar-pilar rumahnya untuk melambangkan perlawanan sekaligus mengungkap keinginan untuk memiliki kebebasan.
Perempuan dalam budaya Madura dipandang sebagai bagian dari keluarga yang harus dilindungi, dirawat, dan sebagai (sumber) perjuangan bagi laki-laki untuk menumbuhkan harga diri di depan masyarakat (Wiyata, 2002). Kata-kata ‘dilindungi dan dirawat’ juga menunjukkan bahwa, pada saat yang sama, ekspektasi budaya (patriarki) menyangkal kemampuan perempuan untuk memilih jalan mereka sendiri dan membatasi kebebasan perempuan atas pemenuhan tubuh, keinginan, dan kebutuhan mereka. Konsekuensi dari pelanggaran ekspektasi sosial budaya tersebut, yaitu perempuan di Madura bisa dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral, membawa nasib buruk, dan aib bagi keluarga serta masyarakat.
Perempuan Madura mengalami tekanan budaya dan struktural terutama bagi yang berasal dari keluarga miskin. Karya-karya Muna Masyari kerap menggambarkan gadis-gadis Madura dari keluarga miskin yang hidupnya terkait dengan perjodohan—bahkan sejak mereka masih dalam rahim ibu. Praktik perjodohan dan pernikahan dini tetap ada karena tekanan struktural. Orang tua, pemimpin agama, dan aparatur negara memainkan peran penting, memastikan praktik ini terus berlanjut. Alasan orang tua mengatur perjodohan dini untuk putrinya beragam, mulai dari masalah keuangan, menjaga kehormatan keluarga, hingga kehormatan agama. Situasi inilah yang oleh Young digambarkan sebagai ketidakberdayaan perempuan karena mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak adanya kebebasan atau otonomi (2004) atau kurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan terhadap kehidupan masa depan mereka. Akibatnya, mereka berada dalam situasi sulit karena posisi mereka yang lebih rendah dalam keluarga di mana keputusan dibuat oleh laki-laki sehingga mereka menjadi korban dominasi dan komodifikasi laki-laki.
Perempuan dan Keibuan di Madura
Isu ini mengacu pada tema penting dalam karya Dwi Ratih Ramadhany berjudul “Silsilah Duka” (2019) yang dengan jelas menggambarkan keibuan dan praktik keibuan dalam konteks Madura. Novel ini sangat menyentuh pemahaman dan perasaan manusia tentang sisi gelap menjadi seorang ibu dan menantu perempuan. Dalam novel ini Dwi Ratih Ramadhany menggambarkan ibu, keibuan, dan praktik keibuan di Madura yang terkait erat dengan budaya dominan dan mitos yang lazim, terutama mitos seputar ibu dan bayi. Karya ini membuktikan bahwa ekspektasi budaya menjadi alat paling tajam untuk menindas perempuan yang akhirnya membuat protagonis perempuan bunuh diri. Menurut Addrienne Rich dalam buku Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (1976), ideologi keibuan disebut ideologi patriarki yang menindas perempuan sehingga membuat perempuan terperangkap tanpa jalan keluar dan menanggung beban batin. Ideologi patriarki yang berlaku dalam masyarakat Madura membangun dikotomi antara ‘ibu yang baik’ dan ‘ibu yang buruk’, yang mengakibatkan perempuan Madura diobjektivikasi oleh patriarki.
Perempuan dan Identitas di Madura
Tokoh perempuan dalam karya-karya Royyan Julian sebagian besar digambarkan sebagai nonmuslim dan non-Madura. Tokoh protagonis perempuan dari cerita pendek Royyan Julian yang berjudul “Di Malam Bulan Darah, Mogut Menyantap Jenazah Orang Kafir” (2019) adalah seorang Tionghoa dan dianggap sebagai nonpribumi—suatu keyakinan yang masih bertahan di benak banyak orang Indonesia—meskipun tokoh tersebut menghabiskan sepuluh tahun hidupnya di sebuah desa. Melalui cerita pendeknya, Royyan Julian dengan jelas menggambarkan dinamika gender, kekuasaan, dan identitas yang timpang dalam budaya Madura.
Royyan Julian menceritakan protagonisnya sebagai seorang perempuan, Tionghoa, dan Kristen yang tinggal di sebuah desa yang menganut sistem patriarki, penduduk asli Indonesia, dan mayoritas muslim. Terlepas dari kenyataan bahwa tokoh protagonis tersebut memiliki sikap yang baik dan hidup harmonis dengan tetangganya, hal itu tidak menghalangi beberapa penduduk desa untuk berprasangka buruk terhadapnya. Identitasnya yang berbeda menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan bahkan setelah tokoh perempuan tersebut meninggal.
Tokoh protagonis perempuan ini juga mengalami apa yang disebut Young sebagai imperialisme budaya, yaitu menyadari dan mengalami bahwa status quo lebih diterima dalam masyarakat sehingga perspektif atau pandangan unik dari kelompok tertentu menjadi tidak terlihat atau diabaikan sambil menstereotipekan dan memarginalkan kelompok tersebut sebagai yang liyan. Oposisi biner antara tokoh protagonis dan antagonis mengungkapkan relasi yang tidak setara antara kedua tokoh tersebut karena tokoh antagonis adalah representasi dari kelompok mayoritas (laki-laki, Indonesia, muslim) dan protagonisnya adalah bagian dari kelompok minoritas (perempuan, Tionghoa, Kristen). Tokoh antagonis digambarkan memiliki kekuasaan untuk menindas sehingga menempatkan tokoh protagonis perempuan dalam posisi yang marjinal dan tidak berdaya.
Perempuan sebagai Sumber Penindasan
Karya sastra Muna Masyari dan Dwi Ratih Ramadhany mengungkapkan bahwa laki-laki bukanlah satu-satunya sumber penindasan perempuan. Perempuan juga memainkan peran penting. Tokoh perempuan digambarkan sebagai pelaku ketidaksetaraan gender, menghalangi perempuan lain untuk mencapai masa depan yang mereka inginkan. Hal ini terlihat dalam karya sastra berjudul “Rumah Hantaran” dan “Silsilah Duka”. Peran para ibu dalam kedua cerita itu membuktikan bahwa perempuan sering bertindak sebagai penganut dan pendukung patriarki. Mereka menyangkal adanya kemungkinan perempuan lain untuk memiliki pilihan dan tujuan yang berbeda, bahkan menolak nilai-nilai patriarki yang berlaku. Femininitas yang diidealkan tentang bagaimana menjadi gadis dan ibu yang baik nan sesuai dengan nilai-nilai patriarki mampu membatasi serta menghalangi perempuan untuk dapat mengejar tujuan, kebutuhan, juga keinginan mereka sendiri. Hal itu menjadikan beberapa perempuan menjadi sumber penindasan bagi perempuan lain. Namun, dalam ruang keterbatasan mereka, beberapa perempuan mampu menolak pembatasan sosial dan budaya yang diberlakukan dengan cara mereka sendiri, sedangkan beberapa lainnya tidak.
Perempuan tentu tidak berniat menindas perempuan lain karena mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak melanggar aturan dan norma yang ada. Masalahnya adalah bahwa aturan dan norma yang mereka berlakukan pada orang lain bersifat patriarki dan membatasi ruang gerak perempuan. Banyak perempuan tidak menyadari hal tersebut karena sudah tertanam di otak mereka dan diwujudkan dalam perspektif serta praktik kehidupan sehari-hari. Kita telah menjadi begitu terbiasa dengan ideologi patriarki sehingga sering kali tampak tidak terlihat sehingga sulit untuk dikenali. Walaupun tokoh-tokoh protagonis cerita kemungkinan besar sulit untuk menghindar dari keyakinan dan praktik patriarki tersebut, penulis juga menyediakan ruang-ruang bagi tokoh protagonis untuk mengungkapkan posisi dan resistensi mereka.
Dari diskusi ini terungkap bahwa nilai-nilai masyarakat patriarki dan ketidaksetaraan gender terlihat di beberapa karya sastra oleh penulis Madura seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, pembahasan tersebut sejalan dengan keprihatinan feminis tentang relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Madura. Ketidaksetaraan kekuasaan terlihat dalam relasi perempuan dan laki-laki di Madura.
Dengan demikian kehidupan perempuan di Madura dalam karya sastra sangat terkait dengan ekspektasi sosial dan budaya. Muna Masyari, Dwi Ratih Ramadhany, dan Royyan Julian secara menakjubkan menciptakan cerita dan tokoh-tokoh perempuan mereka di situasi tertentu dalam konteks Madura. Karya-karya mereka, sebagai produk budaya, berfungsi sebagai refleksi sekaligus kritik karena mencerminkan norma-norma sosial dan budaya masyarakat Madura dan, pada saat yang sama, mampu memberikan kritik terhadap dominasi nilai-nilai patriarki. Isu-isu yang terlihat seperti perjodohan dini, ketidaksetaraan gender, dan ekspektasi sosial-budaya memberi peluang bagi kita—sebagai pembaca—untuk memahami dan mencerminkan perjuangan yang dihadapi oleh perempuan Madura, terutama dari kelas bawah dan minoritas.
Erika Citra Sari Hartanto merupakan dosen di Program Studi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Kini tengah menempuh studi doktoral Ilmu Susastra di Universitas Indonesia.
Editor: Putri Tariza