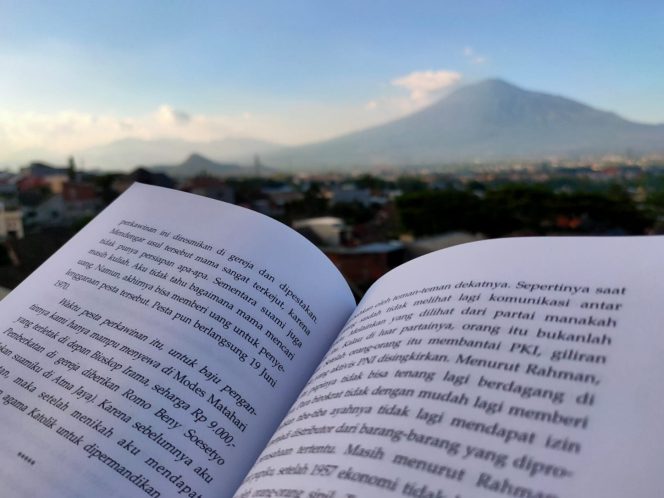Sumpah, tidak ada jalan lain untuk mengarungi pahit getirnya trauma, sesal Slavoj Žižek, filsuf Slovenia, selain terus mengupayakan untuk mengungkit-ungkit trauma itu sendiri. Tapi sebaliknya, orang justru menumpahkan darah, menguras keringat, dan mengeringkan tulang, berusaha untuk melupakan kerusuhan politik yang menorehkan luka bersama yang mendalam dan tak tersembuhkan.
Jangankan memori, tubuh mengingat lara, bahkan bila hilang ingatan sekalipun, nyeri akan tetap terasa. Kata orang, seiring bergulirnya waktu, luka bisa sembuh dengan sendirinya. Tidak, para korban hanya semakin akrab dengan luka itu, sebagaimana tokoh Lely dalam Pecinan Kota Malang yang mengakrabi trauma, depresi, dan luka-luka mental lainnya, hingga semua itu ia anggap biasa. Depresi dan trauma. Bayangkan, bila seseorang berkawan baik dengan mereka. Betapa orang itu akan menjadi objek pasif, terkapar pasrah dipukuli keduanya dengan sukarela!
Pecinan Kota Malang ditulis dalam kurun waktu satu tahun, dari 2003 hingga 2004, sebagaimana telah dibubuhkan dalam babak pembuka. Setiap barisnya mengutarakan hasrat besar Ratna Indraswari Ibrahim yang melatari gugus kelam penciptaannya. Novel ini bukan romansa yang berlumur madu bermandi bunga, melainkan kisah yang dinarasikan langsung dari suara-suara korban kerusuhan politik yang mendera Etnis Tionghoa. Penulis, Ratna Indraswari Ibrahim sendiri berdarah campuran Minang-Tiongkok. Mungkin bantaran inilah yang membuat Ratna Indraswari Ibrahim berbagi rasa dengan Frantz Fannon; memberontak pada kekangan trauma yang dianggap tabu, sebab luka yang terkenang sudah menyesakkan dadanya dan memberangsang ubun-ubunnya.
Pecinan di Kota Malang, sebagai latar tempat novel ini, tak bersolek dalam eksotismenya, tidak terbuai dalam misi komersial hidden gem-nya, tidak pula menjajakan pamor cece-cece ayu dan terkenal pandai berdagang. Akan tetapi, Pecinan Kota Malang menunaikan wasiat Edward Said bahwa sejarah memang sudah disodorkan pada sebuah bangsa, baik berupa arsip maupun tutur cerita. Meski begitu, bukan berarti sejarah sudah purna tugasnya. Sejarah dari sudut pandang korban masih belum sepenuhnya terbaca. Bagi saya, Pecinan Kota Malang menyusup untuk mengisi keretakan ‘yang tak terbaca’.
Sisi ketidak-terbacaan itu bisa diruntuhkan melalui pendekatan sejarah yang dituturkan para korban; suara, dilema, dan pascatrauma mereka. Korban dalam Pecinan Kota Malang mengakumulasi tiga kerusuhan sekaligus usai Indonesia merdeka; G30S PKI, Peristiwa Malari, dan kasus Pemerkosaan Etnis Tionghoa. Melalui sudut pandang Anggraeni dan Lely—namun lebih dominan Anggraeni—novel ini tidak hanya menjabarkan perbedaan Tionghoa Baba dan Totok, tapi juga membeberkan kebencian kolektif pribumi atas Tionghoa Totok.
Memang, Stuart Hall sendiri memaklumi perbedaan fisik antar ras sebagai pendekatan yang justru positif dan natural. “Kalau bisa,” katanya, “Toleransi tumbuh dari faktor pembeda. Bukan malah sibuk menyatakan kesamaan-kesamaan.” Sedangkan, dalam salah satu babak di Pecinan, Anggraeni dan Lely merasakan imbas dari kerusuhan tersebut perkara mata mereka lebih sipit. Namun, sebagaimana yang sudah dikhawatirkan Stuart Hall, perbedaan ini bila menjadi objek disposisi kekuasaan akan menyulut kerusuhan berbasis etnis.
Etnis Tionghoa dalam novel ini dibagi menjadi dua; Totok dan Baba. Bila dibandingkan, Tionghoa Totok kerap menjadi target kebencian kaum pribumi. Pada peristiwa Malari tahun 1972, misalnya. Orang Tionghoa Totok dianggap sebagai sekelompok orang yang merebut kesempatan dagang kaum pribumi. Mereka dianggap kelompok pendatang baru yang tujuannya mengusik kestabilan ekonomi.
Kerusuhan tersebut melatari pertikaian mental dan identitas, khususnya pada diri Anggraeni yang bertubi-tubi mencanangkan bahwa dalam dirinya mengalir darah keturunan pahlawan yang turut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Sampai di paruh awal, Anggraeni meyakinkan identitasnya tersebut pada bapaknya kalau darah Tionghoa-nya paling cuma 40%, sisanya adalah Indonesia. Semua itu untuk mengukuhkan pada pembaca bahwa ras Tionghoa tidak bisa dengan semena-mena menjadi objek disposisi kekuasaan atau kebencian akumulatif.
Namun apalah daya, semua sudah terlanjur, kebencian akumulatif yang menimpa ras Tionghoa kiranya sama dengan kecelakaan pikir yang digadang Frantz Fannon; cognitive dissonance. Rasa benci atas mereka nyaring dibicarakan di novel, meskipun tidak terlalu dalam (mungkin karena sensitif dan tabu). Kebencian ini diturunkan dari masa ke masa, sehingga, sulit bagi orang pribumi untuk tidak membenci kaum Tionghoa. Dalam kasus G30S PKI contohnya, orang Tionghoa baik yang Baba maupun Totok, sekonyong-konyong dituding sebagai komunis. Begitu pula api penyulut kasus pemerkosaan perempuan-perempuan Tionghoa, mereka selalu dianggap sebagai pendatang dan perampas.
Keadaan yang sama juga digadang Mary Douglas dalam bukunya Purity and Danger. Douglas menyinggung riak matter out of place untuk menyebut suatu golongan yang secara simbolik tidak semestinya berada di tempat tertentu. Ia menggunakan analogi ‘kotoran’; kita tidak tergerak untuk menyingkirkan kotoran di kebun, karena memang di situlah tempatnya. Tapi kalau kotoran itu berada di kamar, kita akan menyingkirnya. Hal serupa juga dibahas di Pecinan Kota Malang, Anggraeni dan Lely merasa seperti stateless di kota kelahirannya sendiri atau merupa Odysseus yang dikutuk tak pernah kembali ke rumah yang ia rindukan.
Pecinan Kota Malang tidak terjerumus pada batasan-batasan tertentu seperti masa, konflik, dan kronik sastrawi. Novel ini tidak terpancang pada penanggalan yang teratur atau bahkan runyam. Meski batasan secara kronik maupun fenomenologi tidak menjadi rintangan dalam gagasan, bukan berarti Pecinan Kota Malang tidak fokus pada tragedi atau kerusuhan tertentu. Justru, ini menjadi titik paling mengesankan; Pecinan Kota Malang adalah narasi lenggang yang berpijak pada korban itu sendiri. Lely dan Anggraeni dijabarkan secara utuh, dua anak bangsa yang melintasi tiga kerusuhan dan serangan psikologis. Duka, lara, senja, remaja, kehidupan Lely dan Anggraeni diulas dengan lugas.
Kiranya kelugasan khas Ratna Indraswari Ibrahim terbit dari bidang jurnalisme yang ditekuninya. Setiap gagasan yang ia utarakan padat berisi dan tidak bertele-tele. Setiap kejadian dan perpindahan plot juga tidak diawali dengan pembuka yang mendayu-dayu. Susunan kalimat tidak memiliki irama sama sekali dan tak ada unsur puitik dalam novel ini. Saya tidak melihat hal itu sebagai kelemahan Pecinan Kota Malang. Karya sastra tidak harus menunaikan kaidahnya. Buah pikir yang lugas tentang kemanusiaan dari seorang penulis tentu tidak mengurangi nilai karya seninya.
Secara personal, menurut saya kehidupan Lely adalah yang paling menggelitik. Ia mempertanyakan identitasnya sebagai peranakan Tionghoa yang mendapatkan pola asuh tidak tepat dari bapaknya (sampai bisa mengundang tangis pembaca), dan sampai dia tua sekalipun, Lely masih harus berperang melawan konflik mental dan batin tersebut. Tokoh Lely, sejauh saya merujuk berbagai wacana, bisa menjadi objek riset teori psikologi yang belum menguak trauma masa kecil dan pascatrauma kerusuhan.
Lely mewakili anak-anak yang tumbuh tanpa mengenal cinta dan merepresentasikan cinta sebagai sesuatu yang tidak bakal ia dapatkan. Sampai akhir, tokoh Lely juga masih terjebak dalam dilema hidup yang tak berujung. Dia juga tetap menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dua karya adiluhung Fyodor Dostoevsky, yakni Brothers Karamazov dan Crime and Punishment, pada bagian akhir menemukan jalan spiritualitas dan kedamaian, Pecinan Kota Malang sangat apa adanya. Agak nihilis kalau boleh saya berkata. Cukup nihilis sehingga tidak membebani tokoh-tokohnya untuk insaf di awal, tengah, hingga akhir kisah.
Sukar untuk tidak menggandrungi Pecinan Kota Malang, sulit untuk tidak memeluk keterbukaannya atas luka para korban. Tidak cukup untuk mengetahui ada kerusuhan di sini dan di sana. Pecinan Kota Malang sangat apa adanya, sebagai kehidupan itu sendiri, sebagaimana para korban yang banyak berpasrah dan pada akhirnya menyalahkan diri mereka sendiri.
Lantas, apakah novel ini mengungkit luka lama dan menimbulkan kemarahan baru? Apakah novel ini membuka jalan bagi pembacanya dan para korban untuk menunaikan dan melunasi dendam? Apa yang saya rasakan justru sebaliknya. Sebagai orang Jawa tulen, saya berutang kata ‘maaf yang setulus-tulusnya’ pada seluruh kaum Tionghoa yang terluka lantaran kemarahan kolektif saudara seetnis saya. Walau kata maaf tak bakal mengubah apapun, terampuni atau tidak, tahap awal untuk menyongsong kebaikan adalah mengakui pernah berbuat apa kita pada etnis yang berbeda.
Bukankah Ayank Michel Foucault sudah keluar dari rantai kripto normatif yang membelenggunya (Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason), melepaskan diri dari kelompok terpenjara pola pikir, dengan menggagas pengakuan dosa dan merangkul para korban?
Putriyana Asmarani adalah penulis cerpen dan esai.
Editor: Asief Abdi